
Moh. Ahlis Djirimu
Di Indonesia, jumlah unit usaha UMKM mencapai 99 persen dari total unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 97 persen dari total tenaga kerja. Usaha tersebut juga berperan besar mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal itu tercermin dari pangsa terhadap pembentukan PDB yang mencapai 60,51 persen dan berkontribusi terhadap ekspor nasional sekitar 15,7 persen dari total ekspor nasional (https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/). Tantangan peningkatan kapasitas UMKM menurut berbagai hasil studi, terkait beberapa aspek, yaitu manajerial, permodalan, pasar, penguasaan teknologi, SDM, dan sentra UMKM. Karena itu, perlu arah kebijakan dan strategi untuk mendorong UMKM lebih berkembang, seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dalam program pengembangan UMKM melalui tiga pilar kebijakan, yaitu korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan (https://www.bi.go.id).
Di Provinsi Sulteng, data bersumber dari Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menunjukkan bahwa rumah tangga miskin (RTM) desil 3 sampai dengan desil 5 potensial dapat menerima KURDA, Kecil, Mikro, Supermikro, Ultra Mikro berjumlah 15.614 RTM di Kota Palu, 25.675 RTM di Donggala, 23.060 RTM di Poso, 19.236 RTM di Tolitoli, 15.236 RTM di Buol, 24.900 RTM di Sigi, 44.672 RTM di Parigi Moutong, 13.821 RTM di Tojo Una-Una, 9.987 RTM di Morowali, 7.913 RTM di Morowali Utara, 35.382 RTM di Banggai, 11.874 RTM di Banggai Kepulauan, serta 2.812 RTM di Banggai Laut. BPS Sulteng 2024 menunjukkan bahwa penduduk usia 25-39 tahun yang berpotensi menjadi petani milenial cukub banyak yakni 100,44 ribu jiwa di Kota Palu, 70,14 ribu jiwa di Donggala, 57,79 ribu jiwa di Poso, 53,15 ribu jiwa di Tolitoli, 33,98 ribu jiwa di Buol, 62,51 ribu jiwa di Sigi, 103,08 ribu jiwa di Parigi Moutong, 55,14 ribu jiwa di Morowali, 30,32 ribu jiwa di Morowali Utara, 87,66 ribu jiwa di Banggai, 27,53 ribu jiwa di Banggai Kepulauan, serta 17,25 ribu jiwa di Banggai Laut. Pada sisi kelembagaan ekonomi, ada 1.842 BUMDESA dengan jumlah terbanyak di Morowali Utara sebanyak 291 BUMDESA dan di Sigi sebanyak 278 BUMDESA. Per 30 Juni 2024, data pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Sulteng menunjukkan terdapat 2.032 debitur “kecil”, 15.988 debitur “Mikro”, 4.191 debitur “SUPERMI” singkatan dari Supermikro, serta 13.059 debitur “UMi” Ultra Mikro. Di Tahun 2024, debitur kecil meningkat menjadi 2.780 debitur atau mengalami kenaikan sebesar 36,81 persen. Sedangkan debitur mikro meningkat dari 15.988 orang menjadi 23.386 debitur atau mengalami kenaikan 46,27 persen. Sebaliknya, debitur SUPERMI dan UMi mengalami penurunan dari masing-masing dari 4.191 debitur SUPERMI dan 13.059 debitur UMi pada 2023 menjadi masing-masing tinggal 621 debitur SUPERMI dan 7.390 debitur UMi. Dengan demikian, penyaluran penyaluran Kredit Kecil dan Kredit Mikro meningkat masing-masing dari Rp541,08,- miliar dan Rp639,35,- miliar pada 2023 menjadi Rp727,36,- miliar dan Rp979,59,- miliar pada 2024. Sebaliknya, seiring dengan menurunnya jumlah debitur SUPERMI dan UMi, maka penyaluran kedit mengalami penurunan juga dari Rp37,72,- miliar pada 2023 menjadi Rp5,51,- miliar pada 2024 untuk kredit SUPERMI dan Rp54,94,- miliar menjadi Rp33,12,- miliar untuk kredit UMi.
Perbankan perlu melakukan sosialisasi dan diseminasi, pemasaran, yang fokus pada kegiatan mendorong pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan. Capaian penggunaan fasilitas KUR dan UMi di Banggai Raya meliputi Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, masih tergolong relatif rendah dibandingkan di kabupaten/kota lain, walaupun terdapat peningkatan secara year-to-year. Sebanyak Rp260,1,- miliar KUR tersalurkan di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), sebagian besar terserap ke dalam Lapangan Usaha Perdagangan dan Pertanian per 30 Juni 2024.
Sektor perbankan dapat melakukan Peningkatan Kapasitas. Pilar pertama, korporatisasi UMKM dilakukan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dengan membentuk kelompok atau badan usaha, termasuk melalui integrasi rangkaian nilai bisnis, untuk mencapai skala ekonomi dalam memperluas akses pasar dan pembiayaan. Pilar kedua, kapasitas UMKM dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas UMKM melalui inovasi dan digitalisasi proses bisnis sehingga mendukung perbaikan daya saing UMKM. Pilar ketiga, pembiayaan UMKM dilakukan melalui upaya fasilitasi akses pembiayaan UMKM sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas usaha UMKM. Penguatan korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan akses pembiayaan dilakukan melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengembangan UMKM melalui jalur pembiayaan dari Bank Indonesia dapat disinergikan dengan pengembangan UMKM dari OJK melalui jalur Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi atau Securities CrowdFunding (SCF) (Wijoyo, OJK, 2024). Opsi Pembiayaan. Program Layanan Urun Dana dari OJK tersebut (maksimum Rp10,- miliar) merupakan opsi pembiayaan bagi UMKM di samping Kredit Usaha Rakyat (KUR) antara Rp50,- juta – Rp500,- juta), pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Rp 25,- juta, Peer to Peer Lending maksimum Rp2,- miliar, dan Initial Public Offering (IPO) untuk total aset maksimum Rp 50 miliar (emiten kecil) dan maksimum Rp 250,- miliar (emiten menengah). Latar belakang pengembangan UMKM dari OJK melalui Layanan Urun Dana adalah perkembangan fintech yang luar biasa menjadi media bagi Pasar Modal Indonesia berperanserta dan bersinergi memanfaatkan fintech untuk menumbuhkembangkan Pasar Modal Indonesia. Selain itu, menjembatani adanya gap pembiayaan bagi start-up company dan UMKM dengan menyediakan alternatif sumber pendanaan berbasis teknologi informasi, dan menjadi dasar hukum bagi kegiatan Layanan Urun Dana di Indonesia. Naik Kelas Layanan Urun Dana dikuatkan dari sisi hukum dengan adanya POJK POJK 57/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi dan POJK 16/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Sinergi BI dan OJK dalam pengembangan UMKM melalui dukungan terhadap aspek pembiayaan.
Kredit untuk UMKM, terutama Kredit Usaha Rakyat (KUR), tumbuh positif dari tahun lalu secara nominal. Namun, penyaluran Ultra Mikro (UMi) memang mengalami penurunan. Secara parsial, data menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik untuk setiap skema (ini dapat merujuk pada kelas UMKM). Pelaku usaha mikro yang biasanya mengambil skema UMi atau skema KUR - SUPERMI mengalami penurunan debitur. ini perlu menjadi warning, karena dari hasil monev UMKM, Kanwil DJPb menemukan bahwa pelaku usaha mikro menunjukkan kecenderungan untuk "tidak berkeinginan menantang risiko" mengambil kredit lagi. Sementara itu, wawancara terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan KUR menyatakan hasil sebaliknya, mereka cenderung ingin meminjam lagi untuk ekspansi usaha. Kendala di Sulteng masih minim publikasi dan sosialisasi terkait kredit bagi UMKM. Perlu sinergitas antara Pemda dan instansi pembina umi untuk kegiatan pendampingan dan sosialisasi, bisa saja menyisipkan agenda sosialisasi seperti pada waktu peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI).
Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dan monev KUR tidak sampai menjangkau sampai detail data perorangan sehingga tidak dapat memberikan kesimpulan yang pasti. Secara umum memang diduga terjadi shifting dari SUPERMI ke KUR mikro dan kecil karena di perbankan berdasarkan hasil monev, mereka mempunyai mekanisme penawaran ulang KUR kepada debitur yang telah lunas. Pegadaian sebagai satu dari beberapa penyalur UMi saat ini juga menjadi penyalur KUR. Debitur KUR SUPERMI yang secara plafon beririsan dengan plafon UMi diduga sama-sama lebih memilih untuk "naik kelas" ke KUR Mikro.
Namun demikian, terdapat selisih yang cukup besar dari debitur UMi (dan mungkin sebagian debitur KUR Supermi), yang tidak lagi melanjutkan untuk mengakses. Berdasar hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM binaan dan saat kegiatan pemberdayaan UMKM pada bulan Oktober (mayoritas UMKM rintisan) yang menyampaikan laporan penurunan omset dalam periode sekitar 5 bulan kebelakang, dikhawatirkan penurunan debitur (UMi dan KUR Supermi) merupakan bagian dari imbas penurunan omset tersebut.
Saat ini Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sulteng mengalami penurunan dari 9,75 persen pada Triwulan II-2024 menjadi 9,08 persen pada Triwulan III-2024. Untuk pertama kalinya, LPE berada di bawah 2 digit dan berada di bawah angka kemiskinan yakni 11,77 persen. Hal ini menjadi tantangan berat bagi Provinsi Sulteng. Bagi Bank Indonesia dan Sektor Perbankan, berperan secara kelembagaan dalam menganalisis fluktuasi harga kebutuhan pokok setelah sebelumnya BI menginisiasi adanya Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID) dan mekanisme penciptaan kredit. LPE Sulteng sedang menuju pada keseimbangan baru yakni setelah Sektor Pertambangan menjadi andalan. Saat ini, industrialisasi melalui hilirisasi logam dasar membuat kontribusi Sektor Industri Pengolahan mendominasi perekonomian Sulteng. Namun, inklusivitas perekonomian Sulteng masih jauh dari target yang ditetapkan dalam RPJMD Sulteng Periode 2021-2026. Back to agriculture yang selama ini terabaikan dalam strategi pembangunan merupakan cara tepat periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Sulteng Periode 2025-20245 sekaligus menunaikan peta jalan menuju Indonesia Emas 2045.
Sulawesi Tengah selama 10 kuartal terakhir sampai Tahun 2023 mempunyai laju pertumbuhan ekonomi di atas dua digit atau di atas 10 persen. Hal ini memberikan makna bahwa satu dari enam indikator Visi Pembangunan Sulawesi Tengah telah terlampaui, namun kemiskinan dan pengangguran menjadi poin pengurang kinerja tersebut. Kita tidak perlu bangga atas capaian ini karena Sulteng menghadapi tiga masalah sekaligus.
Pertama, provinsi ini menghadapi kutukan sumberdaya (resource curse), daerah kaya, tetapi rakyatnya merana, relatif belum mendatangkan apa-apa bagi penduduknya. Dari sekitar 3 juta jiwa penduduk Sulteng, terdapat 2,3 juta jiwa atau proporsinya 76,67 persen adalah penduduk berusia kerja. Dari jumlah 2,3 juta jiwa penduduk tersebut, 1,6 juta jiwa atau proporsinya 69,56 persen. Sayangnya, dari 1,6 juta jiwa tersebut, tenaga kerja Sulteng yang bekerja di sektor formal dengan jaminan kepastian upah dan jaminan perlindungan sosial lainnya hanya 499,2 ribu orang. Sebaliknya, terdapat 1,1 juta orang adalah pekerja di sektor informal. Hal ini berarti daerah ini, walaupun angka pengangguran turun dari 3,49 persen pada Februari 2023 menjadi 3 persen pada Februari 2023, dan turun lagi menjadi 2,95 persen padaAgustus lalu meningkat menjadi 3,15 persen pada Februari 2024, tetapi daerah ini belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak pada penduduknya yang menganggur sebanyak 58.500 orang.
Kedua, Sulteng adalah daerah yang mengalami Penyakit Belanda (Dutch Disease). Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi mencapai 10,36 persen pada kuartal III 2023 lalu menurun menjadi 9,08 persen pada kuartal III 2024, yang didorong oleh atraktivitas hilirisasi logam dasar nikel, namun, tingkat pendidikan para pekerjanya 58,4 persen berpendidikan SMP/MTs ke bawah, artinya daerah kaya, tetapi kualitas pendidikan pekerjanya sangat rendah. Pada satu sisi, Sulteng menghadapi ancaman quantity loss educated generation dan pada sisi loss quality human resources. Hal ini bermakna bahwa walaupun daerahnya kaya, produktivitas tenaga kerja sangat rendah, kaya tetapi karena dimanja oleh sumberdaya alam melimpah, produktivitasnya rendah, seperti dialami Belanda pada dekade 1950-an ketika temuan ladang gas di laut utara membuat negara ini tergantung hanya pada satu sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui.
Ketiga, daerah ini menghadapi fenomena fatamorgana pembangunan yang akan membuat pemerintah dan rakyatnya terkesima dengan kinerja hilirisasi logam dasar. Hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah nasional, namun kenyataannya, capaiannya hingga sekarang baru mencapai seperempatnya, sedangkan deposit nikel sebagai ”emas hijau” menyisakan sekitar 2 dekade dengan eksploitasi massif. Lalu siapa yang menikmati hilirisasi? Pertama, Pengusaha pertambangan lokal membayar royalty, sebaliknya, karena rezim pertambangan tersentralisasi, dan Pemerintah Pusat memberikan pembebasan pajak (tax holiday) sampai 25 tahun, maka pengusaha smelter asing tidak membayar royalty. Kedua, pengusaha smelter asing mendapat laba, mereka tidak membayar pajak badan karena mendapatkan tax holiday sampai 25 tahun, lalu seluruh labanya dibawa pulang. Ketiga, Pengusaha pertambangan lokal membayar pajak ekspor, sebaliknya, pengusaha smelter asing tidak membayar pajak ekspor dan seluruh produksinya diekspor. Keempat, harga produksi pertambangan yang dibeli oleh perusahaan smelter sangat murah karena posisi tawar pengusaha pertambangan domestik lemah, terkadang kadar nikelnya rendah di bawah 1,8 persen, labanya lebih besar di Indonesia ketimbang di negara asal, karena itu, mereka berbondong-bondong ke daerah kita. Kelima, pengusaha pertambangan lokal membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebaliknya pengusaha smelter asing bebas tidak membayar PPN. Keenam, pengusaha smelter asing dibebaskan dari bea masuk impor mesin sebagai fasilitas dari Kementrian Investasi (eks BKPM), selain itu mayoritas impor perusahaan smelter masih dikenakan bea masuk. Ketujuh, tujuan akhir menjadi produsen baterai terbesar di dunia patut dipertanyakan karena basisnya Nickel Mangan Cobalth (NMC) justru lebih tidak ramah lingkungan ketimbang Lithium Ferro Phosphate (LFP). Inilah kemungkinan menjadi satu dari berbagai alasan mengapa Tesla milik Elon Musk belum jadi investasi kenderaan listrik di Indonesia, lebih memilih negara jiran Malaysia.
Proporsi Sektor Industri Manufaktur Sulteng dalam perekonomian Sulteng mencapai 40,3 persen, namun dengan tingkat upah rata-rata sebesar Rp2,1,- juta setara dengan tingkat upah di Sektor Pertanian, Sektor Industri hanya menyerap 8,4 persen, sebaliknya Sektor Pertanian berkontribusi dalam perekonomian Sulteng hanya mencapai 15,8 persen, tetapi menyerap tenaga kerja mencapai 43,5 persen, termasuk di dalamnya pekerja tidak trampil. Pada sisi lain, Sektor Pertambangan mempunyai proporsi mencapai 15,4 persen dalam perekonomian. Sektor ini hanya menyerap 1,8 persen dari keseluruhan tenaga kerja di Sulteng, dengan tingkat upah lebih tinggi dari Sektor Industri Manufaktur dan Sektor Pertanian yakni upah di Sektor Pertambangan mencapai Rp3,4,- juta.
Kinerja pembangunan antar daerah dalam satu provinsi dapat dikaji melalui Indeks Williamson. Semakin mendekati 0, maka kesenjangan pembangunan antar daerah semakin merata. Sebaliknya, bila Indeks Williamson mendekati 1, maka ketimpangan pembangunan antar daerah semakin lebar. Data BPS menunjukkan bahwa selama periode 2018-2022, Indeks Williamson di Sulteng meningkat dari 0,86 poin menjadi 1,52 poin. Hal ini disebabkan oleh masifnya pembangunan di wilayah Timur Sulteng terutama Morowali, Morowali Utara dan Banggai, mengabaikan masa depan pembangunan Sulteng di sektor pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan dan perikanan. Hal ini dapat berdampak positif semu dan fatamorgana bagi daerah aktraktif tersebut, selain dampak negatif baik bagi daerah asal tenaga kerja maupun daerah tujuan tenaga. Ambil contoh, gas alam asal Banggai dapat memasok listrik di tujuh prefektur Jepang seperti Oita, Kagoshima, Kunamoto, Fukuoka, Nagasaki dan lain-lain, tetapi listrik di Sulteng sering padam. Keadilan dan Pemerataan Pembangunan dapat menjadi isu pembangunan pembangunan berikutnya, karena episode pemerintahan sebelumnya, termasuk pemerintahan saat ini hanya sampai pada otopilot pembangunan, yang bermakna tanpa pemerintahan pun pembangunan berjalan alamiah.
Hasil Kajian Ketimpangan Fiskal Interregional Sulawesi menggunakan data hingga triwulan III 2023, oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu menunjukkan bahwa di Provinsi Sulteng, pada sisi ketimpangan fiskal vertikal, Rasio Kualitas Belanja dan Indeks Kapasitas Fiskal kabupaten/kota terdistribusi dalam kategori sebagai berikut: Pertama, kategori daerah yang Indeks Kapasitas Fiskalnya meningkat, namun Kualitas Belanja menurun. Daerah ini adalah Kota Palu dan Banggai. Kedua, kategori daerah yang Indeks Kapasitas Fiskalnya meningkat dan Kualitas Belanja meningkat. Daerah ini adalah Kabupaten Morowali. Kategori ketiga adalah Indeks Kapasitas Fiskalnya menurun dan Kualitas Belanja juga menurun. Ini adalah kategori paling rendah karena downgraded. Provinsi Sulteng termasuk ada di dalam kategori ini, bersama dengan tujuh kabupaten lainnya yakni Buol, Donggala, Parigi Moutong, Poso, Sigi, Tojo Una-Una, Tolitoli. Kategori keempat adalah daerah yang mempunyai Indeks Kapasitas Fiskal cenderung menurun, tetapi Kualitas Belanjanya cenderung naik. Daerah dua daerah kepulauan yakni Banggai Kepulauan dan Banggai Laut.
Sekali lagi, jika melihat ketimpangan horizontal atau ketimpangan antar daerah, ketimpangan tertinggi terjadi di Provinsi Sulteng, sementara lain ketimpangannya tercatat tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Ini menandakan adalah ketimpangan pembangunan yang menganga di Sulteng sebagai konsekuensi dari logam dasar. Singkatnya, Sulteng dari sisi ketimpangan pendapatan menjadi paling rendah dengan Koefisien Gini mencapai 0,304 poin pada Maret 2023, sementara ketimpangan wilayahnya tercatat sangat tinggi, berbanding terbalik dengan Gorontalo. Kondisi ini tidak terlepas dari ketergantungan Sulteng terhadap tiga wilayah di Sulteng yang terdapat hilirisasi industri logam dasar.
Selain isu inflasi pada Oktober 2024 yang dua di antaranya disebabkan naiknya harga emas dan kangkung. Isu belum inklusifnya pertumbuhan ekonomi Sulteng yang tertinggi kedua di Indonesia relatif belum mendatangkan manfaat berarti bagi kesejahteraan. Hal ini tercermin dari angka kemiskinan Sulteng mencapai 12,41 persen pada Maret 2023 dan 11,77 persen pada Maret 2024 melampaui angka kemiskinan nasional sebesar 9,57 persen.
Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah sepatut beralih dari paradigma Growth Oriented menjadi Equity for Growth atau dari Pertumbuhan Ekonomi sebagai Panglima Pembangunan menjadi Pembangunan bertumpu pada Pertumbuhan Berkeadilan. Caranya pembangunan di sektor pertanian pangan dan hortikultura berjangka pendek yang menciptakan hilirisasi pangan dan hortikultura, perikanan, perkebunan yang saling sinergi dalam kerangka Sulteng Incorporated. Hal ini dapat pula menjadi solusi ketidakpastian harga pangan dan solusi mengatasi kemiskinan makanan di Sulteng. Data BPS menunjukkan bahwa Inflasi Gabungan Sulteng pada November 2023 meningkat dibandingkan inflasi bulan September menjadi sebesar 2,94% (yoy). Sedangkan di bulan November 2024, inflasi mencapai 1,91 persen. Hal ini seiring dengan perkembangan harga beras yang belum mengalami kenaikan signifikan. Masalah klasik di Sulteng, adalah sumber utama inflasi adalah pangan terutama beras, yang ironis terjadi pada daerah yang secara potensial merupakan lumbung pangan di Sulteng. Selain itu, sekitar 77 persen kemiskinan di Sulteng disumbangkan oleh pangan. Strategi Peraturan Daerah Penyanggah Pangan dan adanya Bulog ala Sulteng dapat menjadi solusi karena petani dan pedagang antar daerah yang rasional pasti menjual pangan di daerah yang harganya tinggi yakni di daerah pesisir Timur Kalimantan. Kenaikan harga komoditas beras pada sejak Oktober 2023, di daerah penyangga pangan justru menjadikan daerah ini dengan tingkat kemiskinan yang tinggi seperti Kabupaten Parigi Moutong, Tojo Una-Una, Donggala. Selain itu, terkait isu pangan, belanja daerah dalam rangka ketahanan pangan belum terdistribusi dengan baik, belanja pendukung justru lebih banyak dibandingkan belanja pokok, yakni belanja untuk alsintan justru lebih banyak dibanding belanja untuk bantuan benih. (*)
*) Penulis Adalah Pengajar FEB-Untad

_(1).gif)
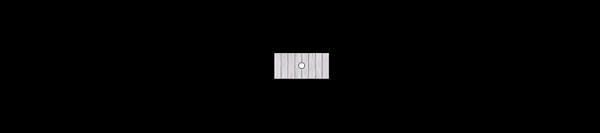










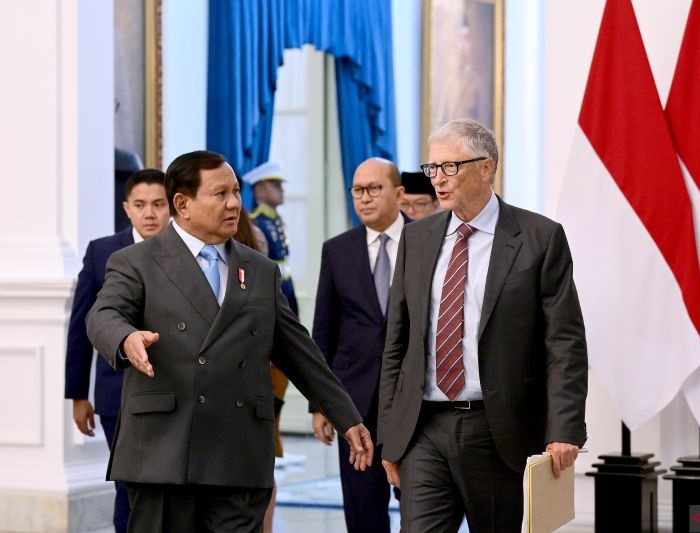




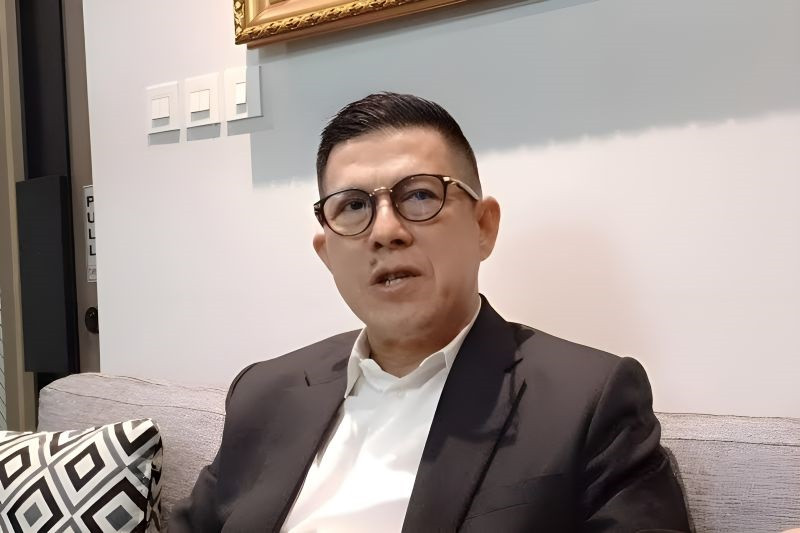







LEAVE A REPLY