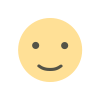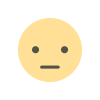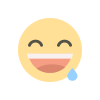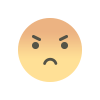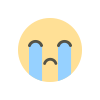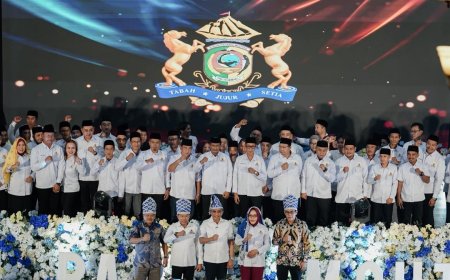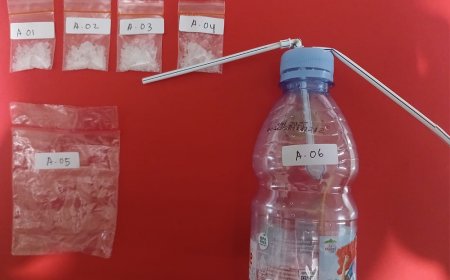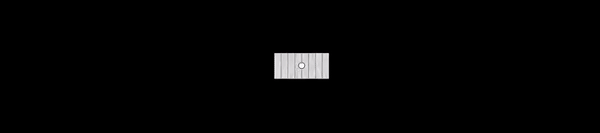Ketika Emas Menjadi Petaka: Membaca Bencana di Sulawesi Tengah dari Palu, Sigi, hingga Parigi Moutong
Oleh: Sofyan Farid Lembah*

SULAWESI TENGAH bukan wilayah asing bagi bencana. Gempa, likuefaksi, banjir, dan longsor telah menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakatnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir—terutama menjelang 2025—bencana di wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Parigi Moutong tidak lagi hanya datang dari alam. Ia tumbuh dari perut bumi yang dikeruk tanpa kendali: Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Di sinilah paradigma baru kebencanaan menjadi penting: bencana tidak selalu jatuh dari langit, sebagian justru lahir dari tangan manusia sendiri.
Pada awalnya, PETI sering dipahami sebagai soal ekonomi rakyat—jalan pintas keluar dari kemiskinan. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas ini telah berkembang menjadi mesin kerusakan ekologis dan sosial:
- Sungai berubah menjadi keruh dan tercemar
- Lereng gunung digali tanpa perhitungan
- Hutan dibuka secara brutal
- Merkuri dan bahan berbahaya masuk ke rantai kehidupan
Di wilayah Palu–Sigi–Parigi Moutong, PETI bukan lagi kegiatan kecil yang sporadis, tetapi aktivitas masif yang membentuk risiko bencana baru: banjir bandang, longsor, kerusakan DAS, dan konflik sosial.
Ketika Negara Absen, Bencana Menjadi Tak Terelakkan
Paradigma lama mungkin akan menyebut banjir dan longsor sebagai “musibah alam”. Paradigma baru justru bertanya: Mengapa bencana terus berulang di lokasi yang sama? Jawabannya sering kali pahit: karena negara gagal hadir sebelum bencana terjadi.
Dalam konteks PETI, kegagalan ini tampak dalam:
- Lemahnya pengawasan
- Tumpang tindih kewenangan
- Pembiaran yang berlangsung lama
- Ketidaktegasan penegakan hukum
Di ruang inilah muncul hubungan tidak sehat antara berbagai aktor: oknum aparat, birokrasi, kepentingan swasta, dan sebagian masyarakat. Bukan selalu karena kejahatan individual, tetapi karena sistem yang permisif terhadap pelanggaran.
Perselingkuhan Kekuasaan dan Normalisasi Kerusakan
Yang paling berbahaya dari PETI bukan hanya kerusakan lingkungannya, tetapi normalisasi kerusakan itu sendiri. Ketika:
- Sungai rusak dianggap biasa
- Lubang tambang dibiarkan menganga
- Banjir dianggap rutinitas tahunan
- Aparat terlihat tetapi tidak bertindak
Maka bencana berhenti menjadi peringatan, dan berubah menjadi kenormalan baru.
Dalam kondisi seperti ini, masyarakat sering ditempatkan pada posisi yang tidak adil: di satu sisi dituntut taat hukum, di sisi lain dibiarkan berhadapan dengan sistem yang ambigu dan penuh kompromi.
Bencana sebagai Produk Pilihan Sosial
Paradigma baru kebencanaan mengajarkan bahwa bencana adalah hasil pilihan sosial dan politik. Di Palu, Sigi, dan Parigi Moutong, pilihan untuk membiarkan PETI berkembang berarti:
- Menerima risiko banjir dan longsor
- Mewariskan kerusakan pada generasi berikutnya
- Mengganti kesejahteraan jangka pendek dengan penderitaan jangka panjang
- Alam tidak pernah sepenuhnya salah. Ia hanya bereaksi.
Belajar dari Kearifan Lokal yang Terpinggirkan
Ironisnya, masyarakat Sulawesi Tengah memiliki tradisi lama dalam menjaga keseimbangan alam—baik dalam adat Kaili maupun komunitas lokal lainnya. Namun kearifan ini sering tersingkir oleh logika eksploitasi cepat dan keuntungan instan.
Padahal, ketahanan masyarakat tidak lahir dari alat berat dan modal besar, melainkan dari:
- Tata ruang yang bijak
- Penghormatan pada alam
- Penegakan hukum yang adil
Negara yang tidak berkompromi dengan kerusakan
Emas atau Masa Depan?
PETI memaksa kita memilih: emas hari ini atau keselamatan esok hari? Jika bencana terus dipahami sebagai peristiwa alam, maka PETI akan selalu punya pembenaran. Namun jika bencana dipahami sebagai hasil dari pembiaran dan perselingkuhan kekuasaan, maka tanggung jawab tidak bisa lagi dialihkan ke hujan, sungai, atau gunung.
Sulawesi Tengah tidak kekurangan sumber daya. Yang sering kurang adalah keberanian untuk berkata cukup.
*) Penulis Adalah Mantan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulteng.
Apa Reaksimu?