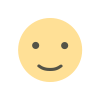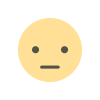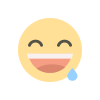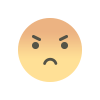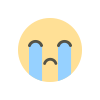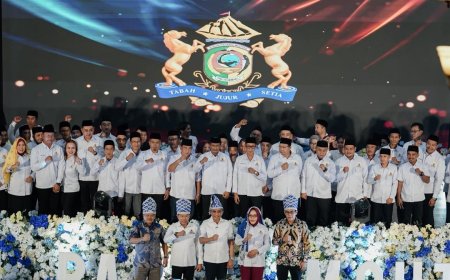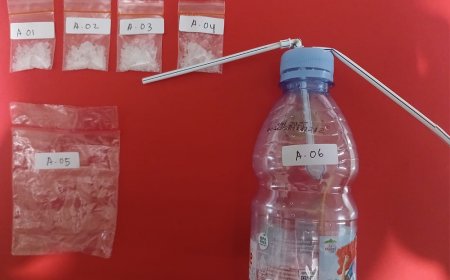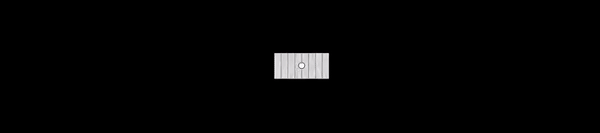Nalar Manusia dan Mesin Cerdas
Oleh Suparman*)

NALAR manusia tengah beradu seru dengan kecerdasan buatan. Di tengah gegap gempita revolusi kecerdasan buatan ini, perguruan tinggi (universitas, institut, sekolah tinggi) memasuki babak baru dalam dialektika perkembangan ilmu pengetahuan. Setiap kampus, fakultas, ruang kuliah, seminar, lokakarya, hingga meja bimbingan skripsi, tesis bahkan disertasi sekalipun, tengah berhadapan dengan fenomena yang tak terhindarkan. Kehadiran mesin yang mampu menulis, menghitung, menganalisis, menyimpulkan, bahkan berdialog layaknya seperti manusia. Tentu saja ada rasa takjub, rasa kagum, tetapi ada pula getir dan gelisah, terutama bagi para pendidik yang selama ini menjadi tulang punggung peradaban akademik.
Namun, sejarah manusia mengajarkan, dalam setiap lompatan teknologi tidak pernah benar-benar menghapuskan peran manusia secara total. Teknologi hanya mampu mengubahnya, memperhalusnya, memperluasanya, dan menuntutnya naik pada level yang lebih tinggi. Perguruan tinggi, sebagai laboratorium akal budi, justru menjadi tempat paling tepat, untuk merumuskan bagaimana manusia dan mesin bekerja berdampingan. Manusia dapat dibantu mesin secara optimal. Dalam konteks inilah, peran dosen mendapat makna baru, dosen bukan lagi sekadar penyampai pengetahuan, tetapi naik level sebagai penjaga nalar, karakter, dan integritas. Dosen membangun dan memberikan kontribusi bagi kemajuan peradaban.
Jensen Huang (2023), CEO NVIDIA, pernah menyatakan, kecerdasan buatan adalah teknologi terpenting pada zaman kita, dan mungkin dalam seluruh sejarah umat manusia. Kutipan Huang itu benar adanya. Dimana, AI (Artificial Intelligence) adalah terobosan monumental dalam peradaban moderen. Tetapi betapapun dahsyatnya teknologi AI ini, ia tidak mampu menggantikan nilai-nilai yang terletak pada hubungan manusia dengan manusia, dosen dengan mahasiswa, sebuah ruang yang menjadi inti dari pendidikan membentuk peradaban.
Peran Tak Tergantikan
Dosen sebagai arsitek pembelajaran. Mereka menafsirkan konteks sosial, ekonomi, budaya, kearifan lokal, hingga aspirasi laiknya seorang perancang, yang tidak hanya melihat data, tetapi memahami lanskap kehidupan dan denyut nadi manusia. AI hanya mampu merekomendasikan materi, menyusun kurikulum adaptif, memberikan materi kuliah yang unggul, dan mengatur ritme belajar mahasiswa yang sesuai. Namun, AI tidak mengalami kehidupan, AI tidak tumbuh dalam masyarakat, AI tidak memahami rasa, dan AI tidak memahami nuansa. AI tidak memiliki kehidupan sosial.
Di ruang-ruang kelas, para dosen dapat membaca ekspresi kebingungan, mendengarkan logat dan dialek, menganalisis gestur mahasiswa, lalu menyesuaikan metode mengajar. AI dapat memprediksi, tetapi tidak dapat merasakan semua itu. Dan pendidikan, seperti segala bentuk seni, bergantung pada rasa dan intuisi. Tanpa rasa dan intuisi, maka proses pendidikan menjadi hambar makna.
Peran dosen sebagai penggerak perubahan pun, tidak hanya berkaitan dengan metode mengajar, tetapi juga menghubungkan mahasiswa dengan realitas kehidupan. Di sinilah peran dosen menjadi jembatan antara teori dan konteks sosial, ekonomi dan budaya. Sebuah peran yang mustahil digantikan oleh algoritme.
Dosen sebagai pembentuk nalar dan makna. Teknologi memberi jawaban, tetapi dosen membangun nalar. Ini adalah batas yang paling fundamental antara manusia dan mesin cerdas. AI dapat menjelaskan teori ekonomi, teori sosial bahkan teori fisika dan matematika, tetapi tidak dapat mengajarkan mahasiswa mengapa teori itu penting untuk kehidupan mereka. Mengapa mereka perlu mempelajari semua itu.
Steve Jobs (2011), seorang visioner yang melihat hubungan erat antara teknologi dan humaniora. Jobs pernah menyatakan, dalam DNA Apple tertanam keyakinan bahwa teknologi saja tidak cukup, maka teknologi harus berpadu dan terintegrasi dengan seni liberal dan ilmu-ilmu kemanusiaan. Kalimat itu menegaskan bahwa teknologi hanya akan memiliki makna ketika disentuh oleh humaniora. Tanpa sentuhan kemanusia, teknologi tak akan terkendali dan membawa disrupsi baru.
Begitu pula dosen, mereka bukan sekadar penyampai konten, melainkan pembentuk cara berpikir dan nalar yang sehat. Dalam wahana diskusi, para pengajar menuntut mahasiswa untuk mengugat asumsi dan preposisi, membedah gagasan dan konseptual, mempelajari bias dan kesalahan, menemukan konteks historis, dan membuat pemaknaan dan tafsiran. Mungkin saja, AI dapat mempercepat semua itu, tetapi AI tidak memiliki kesadaran, AI tidak dapat menemukan nilai.
Mungkin pula AI mengetahui jawaban, tetapi AI tidak tahu mengapa jawaban itu salah atau benar. Setiap arena diskusi memaksa dosen dan mahasiswa, menjelaskan sudut pandang dan pendapat, untuk memeriksa kembali cara berpikir. Ruang ini menjadi tempat bagi dosen mengasah nalar dan membangun logika kritis. Sesuatu yang manusiawi dan tidak dapat digantikan AI. Ruang kelas haruslah menjadi wahana diskusi dan dialog kritis. Ruang kuliah harus menjadi mencerdaskan dan menumbuhkan semangat egaliter dan demokratis.
Dosen sebagai penggerak motivasi dan pembentuk karakter. Tidak ada teknologi, secerdas apa pun, yang mampu menggantikan kekuatan semangat dan inspirasi. Karakter dibentuk oleh keteladanan, bukan oleh algoritme. Mahasiswa percaya kepada seseorang yang mereka lihat berjuang, mereka dengar ceritanya, dan mereka rasakan empatinya. Konteks seperti ini tak mungkin lahir dari mesin cerdas.
Mesin AI dapat menjadi pengingat belajar, tetapi hanya dosen yang dapat berdialog kepada mahasiswa. Kata-kata manusia, terutama dari sosok panutan, mengandung kekuatan afektif yang melintasi batas logika. Lembaga dunia, UNESCO, menyebut dosen adalah makhluk relasional. Karena pendidik dapat membangun relasi, bukan sekadar memberikan materi. Bahkan, di era digital yang paling ekstrem sekalipun, kebutuhan dasar manusia tidak berubah. Kita harus belajar melalui hubungan satu sama lain.
AI tidak mampu memberi nilai etika dan moral, AI tidak mampu memahami luka batin mahasiswa, tidak mampu membaca keraguan yang tersembunyi di balik senyuman. Dosenlah yang mampu membentuk karakter mahasiswa melalui interaksi, keteladanan, karakter dan integritas.
Di era generatif AI, bentuk-bentuk plagiarisme, ketidakjujuran akademik, dan manipulasi tulisan menjadi semakin kompleks dan tak terduga. Dosen menjadi penjaga nilai dan integritas akademik. Model AI mampu membuat tulisan-tulisan yang menarik, riset-riset palsu, bahkan kutipan-kutipan yang tampak benar. Dalam konteks inilah, peran dosen justru semakin penting dan urgen sebagai penjaga moral dan integritas akademik.
Bill Gates (2023) pernah menulis dalam esainya The Age of AI Has Begun, era kecerdasan buatan telah dimulai, dan kita harus memanfaatkannya dengan bijaksana untuk memperluas potensi manusia. Dalam dunia pendidikan tinggi, dosen adalah penjaga etika. Dosen bukan hanya sekedar mengajar apa yang benar, tetapi mengapa sesuatu benar.
Mesin cerdas dapat memprediksi ketidakwajaran, tetapi kesadaran moral hanya bisa lahir dari manusia. Integritas membutuhkan jiwa. Dan jiwa adalah sesuatu yang tidak bisa dimodelkan. Manusia yang membentuk nilai dan integritas akademik itu.
Dosen sebagai pencipta ruang kolaborasi dan diskusi. Sementara, kampus adalah rumah bagi perdebatan. Tempat dimana ide dan gagasan dipertemukan, dipertentangkan, diuji, dibenahi, lalu diperkaya, dan disempurnakan. Diskusi yang hidup dan penuh makna, tidak mungkin terjadi jika setiap mahasiswa hanya berbicara kepada mesin. Ruang diskusi itu tak mampu digantikan mesin. Maka, ruang-ruang kuliah harus diisi dengan diskusi dan dialog yang mencerahkan.
Dalam ruang diskusi, dosen memoderasi ketegangan, menantang argumen, membenahi pendapat, dan kadang membiarkan keheningan atau kegelisahan, untuk memberi ruang mahasiswa berpikir. Para dosen membaca dinamika kelompok, dialektika kelas, merasakan energi ruangan, dan mengambil keputusan spontan dan tepat yang tidak bisa diprediksi algoritme. AI hanya dapat menjadi alat bantu diskusi, tetapi ia tidak mampu menggantikan dinamika emosional, sosial, dan intelektual yang dipandu oleh dosen. Dosen harus membangun nuansa yang tak tergantikan oleh AI.
Kehadiran AI dalam Pendidikan
Elon Musk (2014), dalam berbagai forum, memperingatkan dunia tentang risiko AI dengan mengatakan, kita harus sangat berhati-hati dengan kehadiran AI. Peringatan ini benar adanya. Jika AI digunakan tanpa etika dan integritas, kampus bisa berubah menjadi pabrik efisiensi tanpa kedalaman. Di sisi lain, Bill Gates melihat potensi besar AI dalam memperluas akses. Perspektifnya optimis. Teknologi memberi kesempatan baru bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki tutor atau pengajaran personal. Namun, Gates menegaskan bahwa AI sekedar alat, bukan pengganti dosen.
Mark Zuckerberg (2023), berbicara tentang visinya mengenai superkecerdasan personal. AI sebagai asisten personal superpintar yang membantu setiap orang mencapai tujuan. Namun pertanyaannya: siapa yang mengajarkan mahasiswa menetapkan tujuannya? Siapa yang membimbing mahasiswa memahami etika, moral, integritas dan tanggung jawab dari setiap pilihan? Itulah ruang yang tidak bisa disentuh samasekali oleh AI.
Kampus harus menjadi ruang sinergi. Kampus harus mampu mempertautkan dosen dan kecerdasan buatan. Kampus bukan menjadi wilayah pertempuran antara manusia dan mesin. Alih-alih mempertentangkan manusia dengan mesin, pendidikan justru harus bergerak bersama dalam paradigma sinergi. AI harus menjadi alat untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas dosen, bukan menghapus keberadaan mereka. Pertanyaannya apa yang semestinya dilakukan perguruan tinggi?
Kampus harus menetapkan dan mendesain pembelajaran dengan sistem hibrida. Dimana, kuliah tatap muka difokuskan pada diskusi, debat, dialog, dialektika, bimbingan karakter dan integritas. Sementara itu, AI digunakan untuk personalisasi belajar, latihan adaptif, membangun sifat agility, hingga analisis progres dan dinamika mahasiswa.
Kampus menyiapkan perangkan dalam mengembangkan literasi AI untuk para dosen. Dosen tidak harus menjadi programmer, tetapi mereka perlu memahami cara kerja AI, agar dapat menilai bias, memeriksa akurasi, memahami dinamika, dan memutuskan kapan AI digunakan dan kapan tidak.
Sebelum terlambat, maka segera menetapkan kebijakan etika kampus. Dimana, setiap kampus harus memiliki pedoman etika penggunaan AI: dari penulisan tugas, publikasi, hingga proses monitoring dan evaluasi. Kita semua tahu, bahwa AI bukan musuh, maka harus diberi batasan. AI harus diberikan ruang sekaligus pedoman untuk dijalankan.
Kampus harus memberikan ruang penguatan relasi dosen dan mahasiswa. Karena di era digital, hubungan kemanusiaan justru menjadi lebih penting dan lebih bermakna. Diskusi tatap muka, mentoring, tutorial, dan percakapan personal memiliki nilai yang tak tergantikan oleh mesin.
Investasi Perdaban Manusia
Steve Jobs (2011), pernah menuturkan, teknologi akan selalu lebih bermakna ketika berjalan bersama ilmu-ilmu kemanusiaan. Dunia pendidikan adalah manifestasi paling jelas dari gagasan itu. AI membawa percepatan, tetapi dosen harus membawa kedalaman. AI membawa jawaban, tetapi dosen harus membawa kebijaksanaan.
Jensen Huang menyebut AI sebagai teknologi terpenting sepanjang masa. Elon Musk memperingatkan risikonya. Bill Gates menunjukkan peluangnya. Mark Zuckerberg membayangkan masa depan superkecerdasan personal. Kelima tokoh itu memberi sudut pandang berbeda, tetapi semuanya mengakui satu hal. AI membutuhkan manusia untuk memandunya. Tanpa bantuan manusia, AI tidak dapat bekerja optimal. Dan dalam pendidikan tinggi, manusia itu adalah dosen.
Kampus bukan sekadar tempat mentransmisikan data dan informasi, tetapi arena pembentukan manusia dan peradaban.
Di sinilah AI menemukan batasnya, dan di sinilah peran dosen kembali bersinar cemerlang. AI dapat mengajar dan memberi pengetahuan, tetapi AI tidak dapat membentuk manusia. AI dapat memberi jawaban yang komprehensif dan holistik, tetapi AI tidak dapat memberikan makna dan intuisi. Jika perguruan tinggi ingin menjadi pusat inovasi dan peradaban manusia, maka dosen harus ditempatkan sebagai aktor utama dalam memainkan peran itu, bukan karena dosen tidak dapat digantikan, tetapi karena pendidikan sejati tidak bisa dilakukan tanpa jiwa dan makna. Di era mesin cerdas, peran dan tanggungjawab dosen bukan berkurang. Dosen justru menjadi semakin vital dan urgen.
*) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako
Apa Reaksimu?