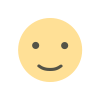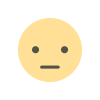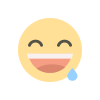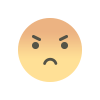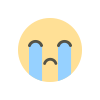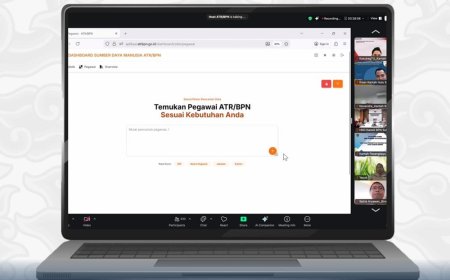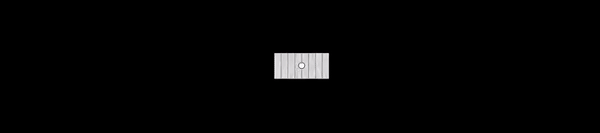Zakat Bukan Pajak: Jawaban Atas Kekeliruan Sri Mulyani Dalam Kacamata Dr.Ali Syariati
Oleh: Mohsen Hasan A, Direktur Studi Islam & Ilmu Filsafat, Dewan Pakar Pusat Partai NasDem,Pemerhati Sosial,Politik,Budaya& Isu Global

PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut zakat dan pajak memiliki fungsi yang sama tentu mengundang perdebatan serius. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya mengandung kerancuan mendasar. Menyamakan zakat dengan pajak bukan hanya keliru secara fikih, tetapi juga menihilkan makna revolusioner zakat dalam kerangka Islam.
Zakat dalam Islam adalah ibadah mahdhah, bagian dari rukun Islam yang landasannya bukan kebijakan politik, melainkan perintah Allah SWT. Besaran, nisab, haul, hingga penerimanya telah ditentukan secara tetap. Zakat bukan sekadar “transfer kekayaan” sebagaimana logika fiskal, melainkan pengakuan bahwa harta manusia mengandung hak orang lain yang wajib ditunaikan.
Ali Syariati menekankan bahwa zakat adalah bentuk revolusi sosial Islam. Ia bukan amal sukarela, melainkan kewajiban struktural yang melekat pada setiap Muslim untuk menegakkan keadilan. Zakat mengikat secara spiritual dan transendental—sesuatu yang pajak, betapapun adil, tidak akan pernah bisa menggantikannya.
Pajak memang memiliki fungsi redistribusi, namun ia adalah produk negara modern yang lahir dari kontrak sosial. Pajak bisa berubah besarannya, jenisnya, dan alokasinya sesuai keputusan politik. Di sinilah perbedaan fundamental dengan zakat: pajak tidak terikat wahyu dan bersifat administratif.
Bagi Syariati, pajak adalah instrumen negara. Tetapi ia mengkritik keras ketika pajak hanya jadi alat memperkuat birokrasi atau elit penguasa. Pajak yang tidak kembali ke rakyat hanyalah bentuk penindasan fiskal.
Mengapa Menyamakan Keduanya Adalah Kesalahan? Pertama, menyamakan zakat dengan pajak berarti mengaburkan dimensi transendental zakat. Seorang Muslim tetap wajib membayar zakat meskipun sudah membayar pajak—karena keduanya lahir dari dua kewajiban berbeda.
Kedua, zakat hanya boleh disalurkan kepada delapan asnaf sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur’an. Pajak tidak mengenal batasan itu. Pajak bisa dipakai untuk proyek infrastruktur, subsidi energi, bahkan pembiayaan politik negara. Maka menyamakan keduanya berarti menihilkan batasan sakral yang telah Allah tetapkan.
Ketiga, dari perspektif Syariati, kesalahan terbesar adalah ketika zakat direduksi menjadi sekadar fungsi fiskal. Itu berarti meruntuhkan kekuatan spiritual Islam yang mampu melahirkan solidaritas sosial, sekaligus menyingkirkan peran moral agama dari ruang publik.
Ali Syariati justru menekankan bahwa zakat dan pajak tidak boleh dipertentangkan, tetapi juga tidak boleh disamakan. Keduanya berjalan paralel: Zakat menjaga kesadaran moral dan solidaritas keagamaan; Pajak menjaga keadilan struktural dalam negara modern.
Jika negara menyamakan keduanya, maka umat akan kehilangan dimensi spiritual dalam ekonomi, sementara negara berpotensi melegitimasi penarikan pajak dengan dalih agama. Inilah bentuk bahaya ideologis yang dikritik Syariati sepanjang hidupnya: agama dijadikan justifikasi kekuasaan.
Sri Mulyani boleh saja berbicara soal peran pajak dalam pembangunan. Namun menyamakan pajak dengan zakat adalah penyederhanaan yang keliru dan berbahaya. Zakat adalah kewajiban ilahi, sementara pajak adalah kewajiban negara. Zakat adalah rukun Islam, sedangkan pajak adalah produk politik.
Dalam kacamata Dr. Ali Syariati, zakat adalah revolusi sosial Islam yang tak boleh direduksi menjadi angka dalam tabel fiskal. Pajak dan zakat memang sama-sama punya dimensi keadilan, tetapi berbeda hakikat. Menyamakan keduanya sama saja menghapus makna sakral zakat dan mereduksi agama menjadi sekadar instrumen administrasi negara.
Zakat bukan pajak. Pajak bukan zakat. Keduanya wajib, tetapi tak pernah bisa disatukan.
Jakarta, 21 Agustus 2025
Apa Reaksimu?