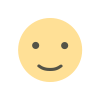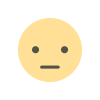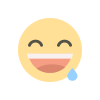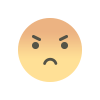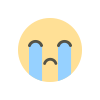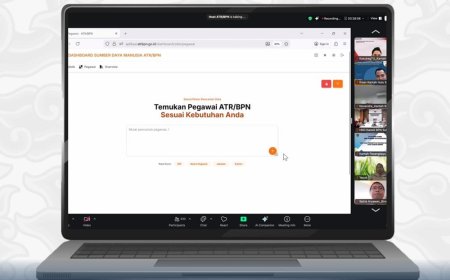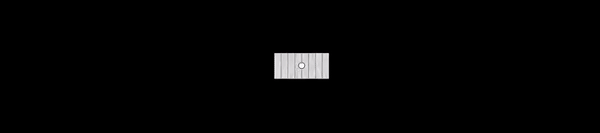Dari Rafflesia Sumatra ke Burung Cendrawasih Papua: Apakah Ini Kolonialisme Ilmiah?
Oleh: Angkasa Putra & Sarifah Aini*

AKHIR-AKHIR ini, media sosial digemparkan oleh penemuan Rafflesia hasseltii di hutan Sumatra Barat. Penemuan ini menjadi sorotan penting tentang peran masyarakat lokal dalam sains serta kolaborasi internasional. Septian Andriki, atau Deki, telah menelusuri hutan Sumatra selama 13 tahun terakhir, menghadapi medan terjal, risiko harimau, dan jalur rawan kriminal demi menyaksikan mekarnya bunga parasit langka ini. Namun, pada pemberitaan awal internasional, nama Deki dan peneliti Indonesia lain hampir tak terlihat. Padahal keberhasilan ekspedisi ini tidak lepas dari kontribusi para ahli dan aktivis lokal yang telah meneliti Rafflesia puluhan tahun, seperti Joko Witono dari BRIN dan Iswandi dari Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sumpur Kudus. Kolaborasi mereka dengan Dr. Chris Thorogood dari Universitas Oxford seharusnya menjadi cerita bersama. Namun saat Oxford mengunggah momen mekarnya R. hasseltii di media sosial, sorotan dunia malah tertuju pada peneliti Inggris itu saja. Namanya ditulis di awal, sementara perjuangan Deki dan tim lokal, yang sudah menunggu kehadiran bunga ini bertahun-tahun tidak disebutkan. Padahal bagi Deki, momen itu begitu mengharukan; ia sampai meneteskan air mata saat melihat bunga yang selama ini ia cari. Meskipun publikasi media sosial resmi Oxford kemudian direvisi untuk menghapus klaim yang menonjolkan nama peneliti Barat, insiden ini memunculkan pertanyaan penting: apakah kontribusi lokal dalam sains masih kerap diabaikan?
Fenomena semacam ini bukan hal baru. Sejak era kolonial, pengetahuan lokal kerap menjadi dasar bagi penemuan ilmiah yang kemudian diatributkan pada peneliti Barat. Contohnya, kisah Rasip dan Marenggé, dua pemburu dari Ternate. Pada 1903, mereka membantu ekspedisi zoologi Belanda di Pegunungan Cyclops, Nugini Utara, mengumpulkan ratusan spesimen burung, termasuk betina Cenderawasih Belah Rotan (Diphyllodes magnificus). Koleksi ini kini tersimpan di Museum Naturalis Belanda, tetapi nama Rasip dan Marenggé nyaris tidak tercatat secara resmi, sementara peneliti Eropa seperti Lorentz dan Beaufort menjadi pusat narasi.
Kedua kasus ini, dari Rafflesia hingga burung cendrawasih, menunjukkan pola serupa: keterampilan lokal dan pengetahuan tradisional sering terabaikan, sementara peneliti Barat menerima pengakuan global. Deki dan timnya menavigasi hutan serta menjaga ekosistem agar Rafflesia tetap tumbuh, sementara Rasip dan Marenggé memanfaatkan pengetahuan lokal untuk memahami perilaku burung cendrawasih dan mengumpulkan spesimen berkualitas tinggi. Namun, narasi resmi tetap menempatkan peneliti Barat sebagai protagonis. Kini, dengan adanya media sosial, masyarakat memiliki ruang untuk bersuara. Publik dapat menilai, mengomentari, dan akhirnya mengubah narasi. Tanpa platform seperti ini, banyak penemuan dari para peneliti lokal mungkin akan terus luput dari perhatian, sementara nama kolaborator asing justru lebih menonjol, baik ada maupun tidak ada kerja sama resmi.
Di sisi lain, perkembangan teknologi dan kebijakan etika riset menawarkan jalan tengah. MoU, perjanjian kolaborasi, dan kebijakan ‘share publikasi’ telah diterapkan untuk memastikan hak peneliti lokal diakui. Dalam dunia publikasi ilmiah, banyak jurnal internasional menekankan pentingnya mencantumkan semua kontributor, termasuk mitra lapangan. Meskipun praktik ini memberi harapan, kasus Oxford memperlihatkan bahwa kesadaran etik tidak selalu muncul secara otomatis, terutama dalam komunikasi populer di media sosial. Pertanyaan yang tak kalah penting muncul: apakah istilah ‘kolonialisme ilmiah’ relevan dalam kedua kasus ini? Yang pasti, peristiwa tersebut menegaskan bahwa setiap kontribusi dalam sains, sekecil apa pun, harus mendapat penghargaan, dan etika riset tidak boleh diabaikan. Paradigma baru diperlukan: pengetahuan dan masyarakat lokal harus menjadi bagian integral narasi ilmiah, bukan sekadar data atau pendukung. Jurnal internasional, media sains, dan platform akademik perlu menyorot kontribusi lokal secara eksplisit, mencerminkan kerja sama sejati antara komunitas lokal dan peneliti internasional. Dengan begitu, sains akan lebih adil dan akurat, mengakui bahwa penemuan bukan hanya hasil individu atau institusi tunggal, tetapi interaksi kompleks antara pengetahuan lokal, keterampilan lapangan, dan metode ilmiah modern. R. hasseltii di Sumatra maupun burung cendrawasih di Nugini mengingatkan kita bahwa sains lahir dalam konteks sosial, budaya, dan ekologis. Mengabaikan kontribusi lokal bukan hanya ketidakadilan moral, tetapi juga merugikan kualitas ilmu pengetahuan itu sendiri. Selain itu, kedua spesies ini bukan hanya sekadar bagian dari biodiversitas Indonesia yang langka, mereka menjadi simbol bahwa narasi ilmiah global perlu berubah, menempatkan pengetahuan lokal sejajar dengan pengetahuan Barat, serta memastikan bahwa orang-orang seperti Deki, Rasip, dan Marenggé mendapat pengakuan yang layak. (*)
*) Penulis adalah PhD Scholar at the Interdisciplinary Program of Marine and Fisheries Sciences and Convergent Technology, Pukyong National University, Busan, South Korea
Apa Reaksimu?