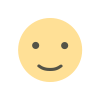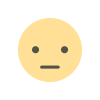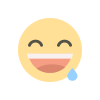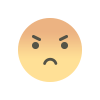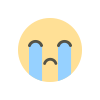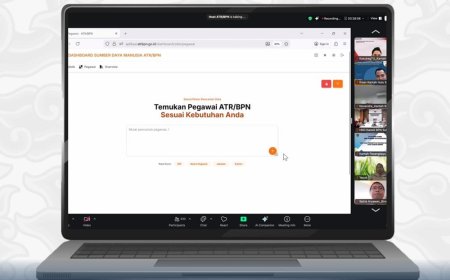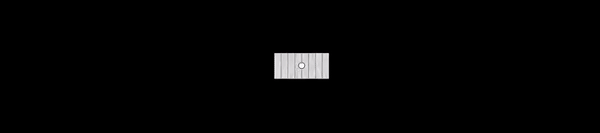Ambivalensi di Balik Semangat Modernitas
Oleh: Randy Rivaldyo, Mahasiswa Pascasarjana Departemen Politik dan Pemerintahan UGM

KOTA-KOTA berkembang sering jatuh pada godaan “simbol kemajuan” memasang ikon kebijakan modern untuk membuktikan diri setara dengan kota besar. Tapi kemajuan tidak diukur dari seberapa canggih alatnya, melainkan seberapa bijak cara kita mengelolanya.
Kota seperti Makassar dengan arus ekonomi yang bergerak cepat, intensitas warga kota yang tinggi, serta jumlah tenaga kerja yang besar menuntut pemerintah reaktif, untuk segera menyediakan layanan moda transportasi yang mampu meredam kemacetan perkotaan.
Berbeda halnya dengan Kota Palu, dengan tingkat urbanisasi dan aktivitas ekonomi yang masih relatif moderat. Kondisi ini semestinya menjadi bahan refleksi bersama : Apakah kehadiran Bus Trans Palu yang menelan dana besar dari APBD benar-benar sepadan dengan manfaat yang dirasakan masyarakat?
Pertanyaan ini barangkali terdengar kurang etis untuk diajukan bagi sebagian orang, terutama bagi mereka yang menganggap Bus Trans Palu sebagai simbol kemajuan kota dan bukti kebanggaan kolektif. Namun, di balik gemerlap citra “modernisasi transportasi,” kita perlu bertanya lebih jujur: kemajuan seperti apa yang sebenarnya kita rayakan?
Niat Baik atau Belanja Popularitas?
Inovasi kerap dielu-elukan, bahkan dipuja sebagai bukti bahwa kota ini sedang bertransformasi. Dua puluh enam bus yang berkeliling di jalur utama kota memang tampak seperti tanda perubahan besar setidaknya yang tampak oleh kelopak mata. Tapi apakah ilusi kemajuan ini sungguh menyentuh realitas keseharian warga?
Euforia terhadap capaian semacam ini seharusnya tidak berhenti pada seremoni peresmian atau kebanggaan sesaat. Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan inovatif benar-benar berkelanjutan dan berpihak pada publik. Jika anggaran daerah terus mengalir tanpa manfaat nyata, maka wajar jika publik mempertanyakan efektivitasnya.
Kerangka-kerangka besi itu tentu tidak dihadirkan hanya untuk berputar di jalanan kota, menjadi koleksi kebanggaan pemerintah, atau bahkan meningkatkan popularitas dan citra kelompok tertentu. Akhir-akhir ini rasanya cukup sulit membedakan antara kebijakan publik yang tampak preventif dengan proyek simbolik yang berada satu panggung, menjaga citra kota yang prestisius.
Langkah inovatif Pemerintah Kota Palu tentu patut diapresiasi. Namun apresiasi tidak boleh menghapus kejujuran kita dalam menilai, adakah dimensi simbolik yang lebih dominan ketimbang manfaat nyata? Apakah ambisi menciptakan transportasi publik yang andal dan terintegrasi benar-benar berangkat dari kebutuhan warga, atau sekadar hasrat tampil sejajar dengan kota-kota besar lainnya?
Fakta menurunnya jumlah pengguna, menjadi cermin bahwa pemerintah lebih sibuk mengejar citra modern daripada menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Berdasarkan temuan yang ada, faktor-faktor seperti biaya operasional yang tinggi, dukungan infrastruktur yang terbatas, serta angka pengguna layanan yang terus menurun menjadi alasan utama layanan Buy the Service (BTS) berhenti beroperasi.
Bandingkan, misalnya, dengan Manado yang lebih memilih moda transportasi konvensional masih lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan transportasi, atau Kendari yang justru lebih dulu gagal mempertahankan layanan bus serupa. Di tengah perbandingan itu, Palu mengambil langkah impresif dengan mengoperasikan 26 unit sekaligus, sebuah gebrakan yang terlihat progresif di permukaan, namun belum tentu mencerminkan langkah yang benar-benar mengayom.
Ironisnya, proyek yang seharusnya bersifat preventif justru berakhir sebagai ambisi gelap. Operasional yang mahal, tanpa kesiapan sosial maupun dukungan infrastruktur, hanya membuatnya tak lebih dari parade kemajuan semu. Bus-bus itu memang bergerak, tetapi yang bergerak mungkin hanya citra dan retorika.
Pada akhirnya, yang tampak bukanlah transportasi publik yang efisien, melainkan panggung politik yang dirancang untuk memupuk popularitas dan membangun legitimasi atas nama tata kota yang modern. Sebuah inovasi yang tampak gemilang di luar, namun masih mencari makna sejatinya di dalam kehidupan nyata warga kota.
Ruang Fiskal yang tak Berkemudi
Kehadiran Bus Trans Palu menghadirkan ambivalensi dalam cara kita memahami logika pembangunan kota. Di satu sisi, program ini merepresentasikan semangat modernisasi, Kota Palu ingin menempatkan dirinya sejajar dengan kota besar lain lewat penyediaan layanan transportasi publik yang terintegrasi dan reliable. Namun di sisi lain, proyek ini juga menimbulkan pertanyaan serius tentang “opportunity cost” Apakah kita benar-benar berinvestasi untuk masa depan, atau sekadar membeli citra kemajuan?
Bayangkan saja biaya operasional setiap bulannya berada di angka Rp1,8 miliar, memaksa pemerintah kota lebih bijak dalam mengelola anggaran. Sementara keuangan daerah terus disedot oleh kerangka-kerangka besi yang hanya bergerak menghasilkan emisi. Ketika ruang fiskal daerah makin sempit disaat prioritas pembangunan lain menanti, wajar jika publik mulai mempertanyakan legitimasi alokasi dana sebesar itu.
Sebagian pihak mungkin memandang langkah ini sebagai strategi pencegahan yang rasional, lebih baik bertindak sekarang sebelum kemacetan benar-benar menjadi masalah. Secara teoritis, langkah proaktif memang bisa lebih hemat ketimbang menunggu lonjakan arus lalu lintas yang menutupi bahu jalan.
Kendati demikian, pilihan tersebut tidak kemudian langsung merubah perilaku masyarakat. Perubahan perilaku hanya akan terjadi jika pembentukan kebiasaan (habit formation) dikerjakan dengan cara yang tepat, seperti menyesuaikan kebutuhan secara bertahap, membuatnya menguntungkan bagi pengguna, hingga menjadikannya pilihan utama.
Sayangnya, Kita sering lupa, perubahan perilaku tidak bisa dipaksa melalui regulasi. Ia hanya tumbuh melalui pengalaman positif yang berulang, layanan yang bisa diandalkan, waktu tempuh yang pasti, serta jaminan rasa nyaman.
Antusiasme warga setelah tarif diberlakukan pada 1 januari 2025 menunjukkan adanya penurunan pengguna dibandingkan masa uji coba gratis. Artinya, masalahnya bukan pada harga tiket atau ketersediaan armada, tapi cara kita membangun kebiasaan dan kegagalan kita menghadirkan pilihan.
Peluncuran 26 unit bus di empat koridor sekaligus memperlihatkan kegagalan dari niat baik menuju ambisi gelap yang tidak berangkat dari kebutuhan riil warga. Kebijakan yang tampak besar dan progresif ini memperlihatkan lompatan yang beresiko. Alih-alih mendistribusikan manfaat, bus-bus itu malah menjadi simbol beban fiskal yang berputar di jalanan tanpa kejelasan arah.
Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan reliable tanpa menyoroti bangunan infrastruktur sosial hanya akan berakhir pada eksperimen-eksperimen seperti yang sudah-sudah. Pemerintah kota seharusnya tidak hanya berinvestasi pada infrastruktur fisik yang berdiri sepanjang bahu jalan, hal yang lebih mendesak ialah membangu infrastruktur sosial dengan logika kebijakan yang peka terhadap perilaku manusia.
Perubahan sosial tidak lahir dari instruksi administratif, melainkan dari desain kebijakan yang mampu membuat pilihan baru terasa lebih mudah, lebih menguntungkan, dan pada akhirnya relevan bagi masyarakat.
Pertanyaan yang seharusnya dijawab bukan lagi soal “berapa banyak bus yang akan beroperasi” tetapi dengan cara apa kita bisa secara bertahap mendorong penduduk perkotaan menemukan alasan rasional dari penggunaan transportasi publik, sehingga mereka secara alami memilihnya tanpa merasa dipaksa untuk berubah?
Membangun kebiasaan baru memang tidak sesederhana membeli bus baru. Namun, bila kebijakan disusun berdasarkan kebutuhan riil yang tumbuh bertahap dan disertai pengelolaan fiskal yang cermat, bukan tidak mungkin Trans Palu berpeluang menjadi warisan sosial jangka panjang dan bukan sekedar proyek ambisius yang berhenti pada seremoni tanpa perubahan. (*)
Apa Reaksimu?