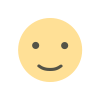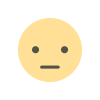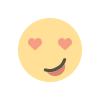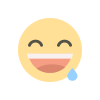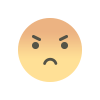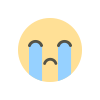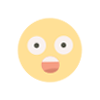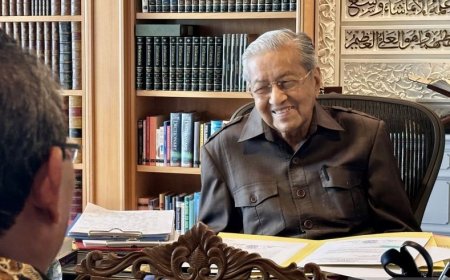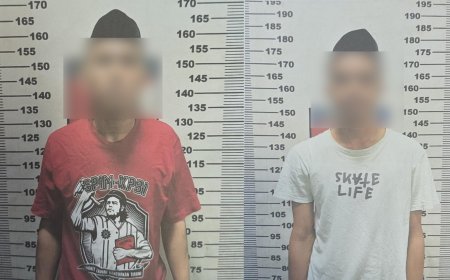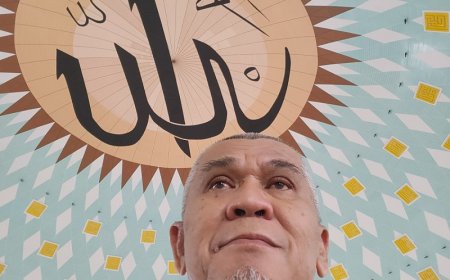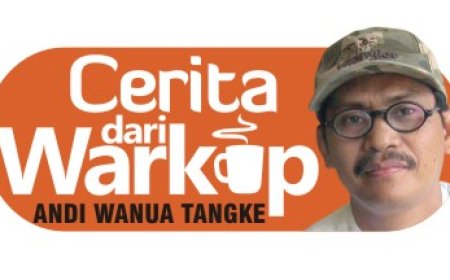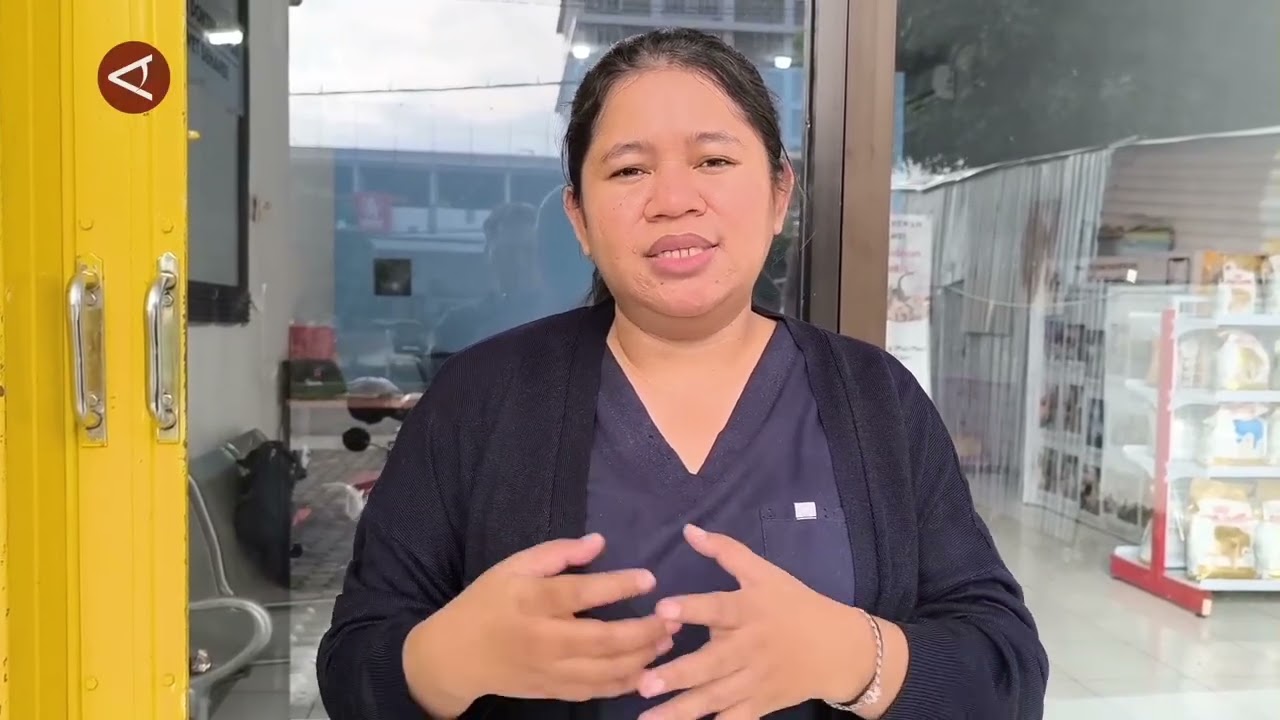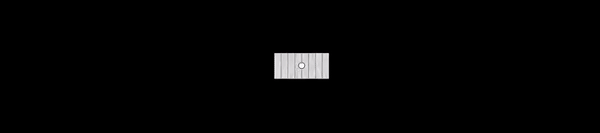Interaksi Pertumbuhan Ekonomi-Kemiskinan-Ketimpangan di Sulawesi Tengah
Oleh: Moh. Ahlis Djirimu*

JUM’AT, 25 Juli 2025 sore, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulteng merilis data kemiskinan dan ketimpangan Maret 2025. Angka kemiskinan menurun dari 11,04 persen per September 2024 menjadi 10,92 persen atau secara absolut turun 0,12 persen. Jumlah penduduk miskin Sulteng pada Maret 2025 sebanyak 356,19 ribu orang atau dua kali lipat dari penduduk miskin Provinsi Sulut atau separuh dari jumlah penduduk miskin Provinsi Sulsel. Jumlah penduduk miskin sulteng ini berkurang sebanyak 2.140 orang dibandingkan dengan kondisi September 2024. Secara spasial, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan Sulteng pada Maret 2025 sebesar 6,98 persen, atau menurun absolut 0,36 poin jika dibandingkan dengan September 2024 sebesar 7,34 persen. Sebaliknya, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2025 sebesar 12,93 persen, malah naik 0,03 poin jika dibandingkan dengan September 2024 sebesar 12,90 persen. Pada September 2024-Maret 2025, penduduk miskin di perkotaan menurun sebanyak 2.930 orang yakni dari 79,85 ribu orang pada September 2024 menjadi 76,92 ribu orang pada Maret 2025. Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan malah meningkat sebanyak 790 orang yakni dari 278,48 ribu orang pada September 2024 menjadi 279,27 ribu orang pada Maret 2025). Lalu Garis Kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp624.854,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp468.788,- atau proporsinya sebesar 75,02 persen), sebaliknya Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp156.066,- atau proporsinya 24,98 persen.
Makna apa terkandung pada data rilis BPS ini? Bila kita menggunakan data historis kemiskinan periode Maret 2014-Maret 2025, selama bulan September-Maret periode tersebut, terdapat 5 kali kenaikan angka kemiskinan dan 4 kali penurunan. Kelima kenaikan angka kemiskinan tersebut terjadi berturut-turut pada September 2014-Maret 2015, September 2015-Maret 2016, September 2016-Maret 2017, September 2021-Maret 2022, dan September 2022-Maret 2023. Sebaliknya 4 kali penurunan angka kemiskinan terjadi pada September 2017-Maret 2018, September 2018-Maret 2019, September 2019-Maret 2020, dan September 2024-Maret 2025. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini, strategi penanganan kemiskinan relatif belum benar-benar tepat secara: spasial, inklusif, tematik, sasaran, mutu, waktu dan tepat administratif, Strategi penanggulangan kemiskinan masih bersifat instan layaknya pemadam kebakaran dan lips service.
Ada kaitan erat antara Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)-Kemiskinan-Ketimpangan atau dikenal dengan Growth-Poverty-Inequality Triangle (GPI triangle) yang pertama kali diperkenalkan Kepala Ekonom Bank Dunia Francois Bourgignon di Pakistan 2005. Pertama LPE akan diikuti oleh Pengurangan Kemiskinan jika minimal 40 persen kelompok miskin naik pendapatannya. Laju pertumbuhan ekonomi Sulteng sebesar 8,69 persen pada triwulan I 2025 menunjukkan bahwa mesin industri pengolahan telah berproduksi, justru hanya menurunkan angka kemiskinan sebesar 10,92 persen pada Maret 2025. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi pun di atas 10 persen pun, tetapi angka kemiskinan belum serta merta turun. Penyebabnya orkestra pelaksana pembangunan Provinsi Sulteng belum berubah paradigmanya dari mengagungkan pertumbuhan (growth oriented) menuju pertumbuhan berkeadilan (equity for growth) termasuk bekerja business as usual.
Sejak lama, kontribusi monokultur beras yakni 24,05 persen di perkotaan dan 25,96 persen di perdesaan, rokok sebesar 12,60 persen di perkotaan dan 12,77 persen di perdesaan, serta ikan tongkol/tuna/cakalang sebesar 3,75 persen di perkotaan dan 4,10 persen di perdesaan. Bukankah beras dan ikan melimpah di Sulteng? Tiga komoditi ini menjadi tiga besar penyumbang naiknya garis kemiskinan, tetapi Pemerintah Daerah hanya punya solusi “pasar murah”. Kemiskinan di Sulteng, secara empiris terjadi pada daerah-daerah yang secara potensial merupakan lumbung pangan di Sulteng. Sulteng mencari akar masalah kemiskinan yang dapat saja berbeda antar masing-masing 13 daerah dan solusi berbasis spasial. Sepatutnya, Pemerintah Daerah baik Provinsi Sulteng dan kabupaten/kota mengeluarkan regulasi penyanggah harga pangan melalui penciptaan Lembaga penyanggah harga yang memenuhi pangan dalam Sulteng lebih diprioritaskan berwujud BUMD Pangan maupun Kawasan Ekonomi Khusus Pangan bagi KEK Palu yang redup menunggu downgraded. Bila surplus, lalu dapat jual ke daerah lain. Tantangannya memang berat, karena mata rantai perdagangan antara pedagang antar daerah dan pengepul telah tercipta abadi, sementara petani di hulu tetap miskin. Satu-satunya daerah yamg mempunyai regulasi penyanggah pangan jagung adalah Kabupaten Buol. Best & Bad practice dari Buol dapat mennjadi pelajaran bagi Sulteng.
Rokok menjadi penyumbang kemiskinan kedua di Sulteng. rokok kretek filter dan rokok elektrik. Walaupun pemerintah sering menaikkan cukai rokok yang mendorong kenaikan harga rokok kretek, tetapi keinginan untuk membelinya tetap ada karena yang “terjajah” adalah pola pikir perokok melalui caffeine. Rokok menjadi penyumbang kedua memiskinkan penduduk Sulteng yang kontribusinya mencapai 12,60 persen di perkotaan dan 12,77 persen di perdesaan. Rokok kretek filter menjadi penyumbang kedua memiskinkan penduduk Sulteng yang kontribusinya dalam pembentukan garis kemiskinan mendorong peningkatan usia perokok semakin muda usia. Dalam masyarakat petani di perdesaan, rokok mempengaruhi mindset bekerja yang hidup dalam tekanan kemiskinan.
Penyebab ketiga adalah ikan laut. Fenomena ini sering dan menjadi aneh di Sulteng. Betapa tidak, Sulteng merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang memiliki empat Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yakni WPP 713 Selat Makassar, WPP 714 Teluk Tolo, WPP 715 Teluk Tomini dan Perairan Halmahera Bagian Barat, serta WPP 716 Laut Sulawesi. Provinsi Sulut dan Gorontalo hanya memiliki 2 WPP yakni WPP 716 Laut Sulawesi dan WPP 715 Teluk Tomini dan Perairan Halmahera Bagian Barat. Provinsi Sulsel dan Sultra hanya memiliki 2 WPP yakni WPP 713 dan WPP 714. Namun, pemanfaatannya lebih banyak dioptimalisasi oleh provinsi tetangga tersebut. Kemiskinan di Sulteng disebabkan oleh perikanan dan kelautan menjadi aneh karena sub sektor yang melimpah di Sulteng. Namun, kontribusi sub sektor ini dalam Produk Domestik Regional Bruto di Sulteng hanya mencapai 6,04 persen atau berada di urutan kesepuluh di Indonesia. Kenyataan ini jauh di bawah kontribusi secara nasional sub sektor perikanan dan kelautan di tetangga seperti Provinsi Sultra (11,32 persen), Sulbar (10,98 persen), Gorontalo (9,17 persen), Sulsel (8,39 persen) dan Sulut (7,64 persen). Singkat, Sulteng melimpah ikan, tetapi nelayannya tetap merana di pesisir, yang proporsi rumah tangga nelayan miskin mencapai 5,34 persen.
Walaupun angka kemiskinan menurun, tetapi Angka Kedalaman Kemiskinan (P1) justru mengalami kenaikan dari 1,72 poin pada September 2024 menjadi 2,21 poin pada Maret 2025. Hal ini bermakna bahwa penduduk miskin di bawah garis kemiskinan cenderung menuju ke dasar jurang kemiskinan. Demikian pula, Angka Keparahan Kemiskinan (P2), meningkat dari 0,41 poin pada September 2024 menjadi 0,61 poin pada Maret 2025. Hal ini bermakna bahwa kesenjangan pendapatan antara penduduk miskin semakin melebar. Strategi mengatasinya adalah memprioritaskan penanganan P1 ketimbang P2.
Kedua, interaksi antara LPE dan Ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi diikuti pengurangan ketimpangan jika yang menopang pertumbuhan ekonomi adalah sektor pertanian khususnya pangan-hortikultura dan perikanan, dan industri manufaktur padat karya. Data di Sulteng menunjukkan bahwa sektor pertanian padat karya, tetapi industri pengolahan padat modal. Pangan-hortikultura dan perikanan belum menjadi panglima pembangunan. Nanti periode RPJMD 2025-2029, pertanian mulai menjadi panglima keberlanjutaan pembangunan. Sepatutnya pertumbuhan ekonomi tinggi diikuti oleh tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun. TPT meningkat dari 2,95 persen pada Agustus 2024 menjadi 3,02 persen pada Februari 2025. Tingkat pengangguran tenaga terdidik lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi tetap dominan. Artinya, SMK dan Perguruan Tinggi menjadi “Gudang calon Penganggur”. Hal ini terjadi pada daerah industri berbasis gas alam yakni Kabupaten Banggai, dan daerah yang berbasis logam dasar nikel yakni Kabupaten Morowali, Morowali Utara, serta Kota Palu sebagai daerah berbasis batuan dan emas akan dibanjiri tenaga kerja. Sulteng mengalami Paradoks Hukum Okun, yang berarti walaupun laju pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi tidak banyak mendatangkan penciptaan lapangan kerja karena sifat industri padat modal. Saat ini pun, LPE berada di bawah 10 persen yakni 8,69 persen, menjadi Kota Palu selalu mempunyai pengangguran tertinggi. Kutukan sumberdaya alam ada di pesisir timur dan pesisir barat Sulteng akan mendapat warisan bencana lingkungan dan laju kehilangan hutan selama 10 tahun terakhir setara 18 ribu lapangan sepak bola.
Publikasi BPS data kemiskinan dan koefisien Gini Maret 2025 menunjukkan, secara umum, ketimpangan di Sulteng menurun dari 0,309 poin pada September 2024 menjadi 0,279 poin pada Maret 2025. Lebih detail lagi, di perkotaan, ketimpangan meningkat dari 0,340 poin pada September 2024 menjadi 0,305 poin pada Maret 2025. Hal ini berarti ada 1 persen penduduk Sulteng menguasai kekayaan Sulteng sebesar 27,9 persen atau hampir sepertiganya. Sementara, ketimpangan di perdesaan menurun dari 0,271 poin pada September 2024 menjadi 0,249 poin pada Maret 2025. Data ini bermakna, bahwa pendapatan perkapita penduduk perkotaan Sulteng tergerus oleh kenaikan 73,32 persen harga pangan, sebaliknya, daya beli masyarakat pedesaan melemah tergerus oleh 75,92 juga oleh harga pangan. Ironisnya, konsentrasi kemiskinan di Sulteng justru terkonsentrasi pada daerah yang secara potensial turun-temurun merupakan lumbung pangan Sulteng.
Hal ini menimbulkan fenomena ketiga yakni, LPE di Sulteng dapat meningkatkan ketimpangan di perkotaan karena pertumbuhan ekonomi ini lebih banyak disebabkan oleh kenaikan pendapatan kelompok 20 persen terkaya di perkotaan yang kenaikannya lebih cepat ketimbang 40 persen penduduk perkotaan kelompok miskin. Sebaliknya, di perdesaan, kenaikan 40 persen pendapatan kelompok miskin, lebih tinggi ketimbang kenaikan pendapatan 20 persen kelompok terkaya. Laju kenaikan pendapatan 20 persen kelompok terkaya 4,8 lebih cepat ketimbang 40 persen kelompok termiskin. Ini pula yang dapat menjelaskan mengapa laju penurunan kemiskinan berlangsung perlahan-lahan pada 5 kali September-Maret periode 2014-2025 walaupun biasanya periode tersebut, masyarakat diguyur berbagai bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan hanya sampai pada Koordinasi bermakna Kopi Susu Rokok dan nasi. Kenyataan ini menunjukkan adanya tiga hal yang patut digarisbawahi. Pertama, daerah-daerah yang mempunyai realisasi rendah anggaran penanganan kemiskinan relatif belum mempunyai sense of crisis terhadap antisipasi kenaikan harga BBM, baik terhadap jumlah penduduk miskin maupun terhadap persentase kemiskinan sebagai akibat dari kenaikan harga BBM bersubsidi pada 2022. Dampak dari lambatnya timing daerah dalam menyalurkan anggaran penanganan inflasi jelas terlihat dari kenaikan angka kemiskinan ini. Kedua, koordinasi antara Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten/kota belum berjalan optimal. Pemantauan atas fluktuasi harga telah dilakukan harian, namun tindaklanjutnya belum menjadi aksi Bersama para pemangku. Ketiga, koordinasi antara Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulteng yang ex-officio dipimpin oleh Wakil Gubernur dan para Ketua TKPK Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh para wakil Bupati/wakil walikota belum berjalan sebagaimana mestinya. Rapat koordinasi hanya menjadi poverty outlook, relatif tanpa rencana tindak lanjut bersama. Hal ini tentu diperparah oleh ketidakpahaman pada implementasi dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) periode 2021-2026 yang masih berlaku sesuai Permendagri Nomor 53 tahun 2020.
Di Sulteng, adanya penguasaan 41 persen perekonomian Sulteng pada 20 persen kelompok penduduk terkaya, akan semakin parah jika fenomena Keempat terjadi yakni ketimpangan pendapatan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika ketimpangan pendapatan terjadi adalah hasil dari sistem insentif bagi peningkatan produktivitas, reward dan entrepreneurship yang justru hanya dimanfaatkan oleh kelompok penduduk 20 persen terkaya, ketimbang 40 persen penduduk termiskin.
Kelima, bertolak belakang dengan fenomena keempat, ketimpangan pendapatan di Sulteng dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi bila ketimpangan menimbulkan rendahnya kohesi sosial, konflik komunal, perkelahian antar desa sebagai dampak dari industri padat modal, kesemrawutan hidup, berpindahnya penduduk dari becocok tanam pangan, perkebunan di pesisir dan pegunungan Kota Palu, Morowali, Morowali Utara ke Kawasan industri dan bencana lingkungan di daerah industri. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada kuartal 1 2025 menurun dari 10,24 persen pada kuartal I 2024 menjadi 8,69 persen pada 2025. Penurunan dari sisi supply side disebabkan oleh kegiatan industri ekstraktif sektor pertambangan berpindah ke sektor industri pengolahan berbasis logam dasar nikel. Mesin-mesin industri di Morowali dan Morut berada pada kondisi sudah berjalan. Kebutuhan akan tenaga menurun, karena semua kawasan industri ini padat modal, walaupun saat ini Morowali dibarengi oleh arus TK masuk rata-rata 55 orang per hari. Artinya, LPE ini menimbulkan anomali pembangunan, yang ditunjukkan Tingkat Pengagguran Terbuka Sulteng pada Februari 2025 meningkat absolut dari 2,94 persen pada Agustus 2024 menjadi 3,02 persen pada Februari 2025.
LPE Sulteng 8,69 persen pada kuartal I 2025 berada di bawah angka kemiskinan Maret 2025 sebesar 10,92 persen karena sekitar 75 persen angka kemiskinan disumbangkan pangan khususnya beras, rokok ikan yang telah dijelaskan di atas. Ini bermakna pula bahwa insentif bibit, pupuk, alsintan, dan lain bersifat time lag, diberikan sekarang, dampaknya nanti terasa di masa datang. Ini terkait erat dengan Nilai Tukar petani (NTP) karena 70 persen penduduk miskin berada di desa dan berprofesi sebagai petani. NTP Juni 2025 sebesar 115,21 poin menurun dari 118,17 poin pada Mei 2025. Turunnya NTP berada pada sub NTP tanaman perkebunan sebesar 4,31 persen, lalu sub NTP Hortikultura sebesar 1,28 persen dan NTN Perikanan sebesar 0,66 persen. Secara keseluruhan mencapai penurunan 6,25 persen. Sebaliknya sub NTP Tanaman Pangan mengalami kenaikan sebesar 0.18 persen dan sub NTP Peternakan meningkat sebesar 3,14 persen atau overall sebesar 3,22 persen. Artinya, jumlah absolut penurunan 3 sub NTP lebih besar ketimbang peningkatan sub NTP dua yang terakhir. Hal ini berarti pula dari hasil usaha petani dan nelayan, jumlah yang mereka terima lebih kecil ketimbang yang mereka keluarkan. Tentu ini menggerus daya beli petani dan nelayan sehingga semakin lemah beriringan dengan daya tawar mereka karena penguasaan tengkulak. Selain itu, saat ini Sektor Pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi penerimaan negara perpajakan terbesar keenam di Sulteng sebesar Rp85,- miliar atau proporsinya 5,25 persen di bawah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp623,- miliar atau 38,71 persen, Sektor Administrasi Pemerintahan sebesar Rp311,- miliar atau 19,29 persen, Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp118,- miliar atau proporsinya 7,35 persen, Sektor Persewaan sebesar Rp109,- miliar atau 6,77 persen, dan Sektor Konstruksi sebesar Rp59,- miliar atau 5,91 persen.
Keenam, ketimpangan tinggi dapat meningkatkan kemiskinan jika ketimpangan disebabkan oleh banyak populasi orang miskin ketimbang orang kaya walaupun kemiskinan dapat saja rendah karena sebagian besar orang masih miskin. Fenomena saat ini yakni penduduk menggunakan tabungan berjaga-jaga dan dissaving dengan berhutang telah menggerus daya beli beriringan dengan fenomena Rombongan Jarang Beli (Rojali), Rombongan Hanya Tanya (Rohana), Rombongan Hanya Mengelus (Roh Halus) pada pusat perbelanjaan.
Ketujuh, ketimpangan tinggi membuat kekuatan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan melemah. Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang hendak dikurangi. Lembaga Perencana di daerah sebaiknya fokus pada esensi perencanaan karena 50 persen keberhasilan pembangunan ditentukan perencanaan. Sisanya yakni Implementasi, evaluasi, feedback, tindaklanjut feedback berbagi proporsi sisanya. Perencanaan sulteng dalam payung Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan secara utuh di sisi hulu mewajibkan adanya semua dokumen utuh mulai RPJPD, RPJMD, RENSTRA OPD, RENJA OPD, dan adanya "jembatan sinkronisasi" perencanaan dan penganggaran dalam payung hukum Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran dalam pembangunan nasional. Selama periode pertama RPJMD 2005-2025, ada 10 missing-link dalam perencanaan pembangunan. Contohnya, Renstra OPD dan Desk Renstra OPD nanti relatif dimulai pada 2021 atau 4 tahun setelah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selama ini, pelaksanaannya adalah planning by accident tiba masa tiba akal. OPD belum biasa bekerja berdasarkan indikator kinerja. Seni perencanaan yang ada manusianya ini belum dipahami filosofinya. Semenjak lebih dari satu dekade yang lalu Sulteng mengalami 4 paradoks pertumbuhan: yaitu tinggi pertumbuhan, tetapi kemiskinan tinggi, tinggi pertumbuhan tetapi jurang ketimpangan antar daerah sangat lebar, adanya kutukan sumberdaya alam, penyakit Belanda yakni daerah yang hanya bergantung pada sektor ekstraktif, adanya fenomena miopik yakni pindahnya penduduk dari sektor primer ke pembangunan awal platform kawasan industri lalu ketika outsourcing ini habis kontrak, mentalitasnya tidak ingin kembali ke sektor primer, serta adanya the Chilean Paradox yakni ketergantungan pada logam dasar nikel menggerus daya beli 40 persen kelas menengah.
Solusinya, transformasi pembangunan dari sifat general ke tematik: stunting, petani dan 5,38 persen nelayan miskin, RT miskin perempuan yang jumlah 31.448 unit atau 9,81 persen dari RT penduduk miskin sulteng, RT miskin difabel, penguatan kelembagaan ekonomi daerah dan masyarakat dan spasial.
Beruntunglah Pemerintahan sekarang mempunyai visi kembali pada pertanian sulteng yang memang masa depan utama. Setidaknya, dengan meletakkan Visi pada Sektor Pertanian, strategi Pembangunan pertanian menjadi Panglima Pembangunan dalam RPJMD. Betapa tidak, Nilai Tukar Nelayan (NTN) selama ini memang masih di bawah 100 poin berbanding terbalik dengan panjang garis pantai sulteng yang mencapai 6.600 km hampir setara gabungan panjang garis pantai Thailand dan Vietnam. Sektor Perikanan dan Kelautan Sulteng yang setiap tahun hanya dapat menghasilkan devisa kurang dari USD2,5,- juta, sebaliknya, kedua negara yang garis pantainya masing-masing 3.300 km dan 3.200 km mendapatkan devisa masing-masing lebih dari USD5,- miliar setahun. Haruskah penduduk Sulteng merana di lumbung pangan dan perikanan?
*) Guru Besar Bidang Ekonomi Internasional FEB-Untad
Apa Reaksimu?