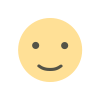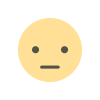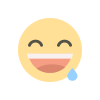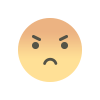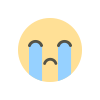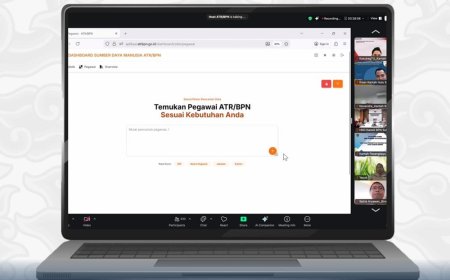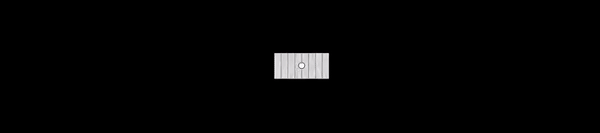Purbaya dan Etika Fiskal: Ketika Integritas Menolak Berkompromi
Oleh Mohsen Hasan A, Pemerhati Sosial, Politik, Budaya & Isu Global - Dewan Pakar DPP Partai NasDem

DALAM suasana politik ekonomi yang sering diwarnai kepentingan kelompok dan proyek-proyek elitis, langkah tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan APBN untuk proyek Family Office di Bali menjadi sinyal moral yang langka bahkan menyejukkan.
Kalimat singkatnya, “Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana,” terdengar sederhana, namun di baliknya terkandung makna besar tentang kedaulatan fiskal dan integritas pejabat publik.
Sudah menjadi rahasia umum, dalam tata kelola ekonomi kita, garis batas antara proyek publik dan kepentingan privat sering kali kabur. Banyak proyek megah dibungkus dengan istilah pembangunan atau investasi strategis, padahal berorientasi pada akumulasi keuntungan kelompok tertentu.
Sikap Purbaya adalah bentuk penegasan bahwa anggaran negara bukanlah dompet oligarki. APBN adalah kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat, bukan sumber dana bagi proyek yang tidak memiliki urgensi publik.
Dengan menolak pembiayaan proyek Family Office, Purbaya bukan sekadar menjaga keuangan negara, tapi juga mempertahankan martabat kebijakan fiskal dari intervensi politik dan bisnis.
Dalam iklim pembangunan yang sering kali berorientasi pada citra dan kecepatan proyek, pejabat yang menolak berkompromi sering dipandang menghambat “kemajuan”. Namun, kemajuan tanpa arah moral justru menjerumuskan.
Sejarah membuktikan: banyak negara jatuh dalam krisis bukan karena kekurangan dana, melainkan karena abainya etika pengelolaan anggaran.
Purbaya sadar bahwa setiap rupiah APBN adalah darah rakyat. Di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih sempurna, beban utang meningkat, dan tekanan fiskal makin berat, menolak proyek non-prioritas adalah bentuk tanggung jawab, bukan perlawanan.
Itulah perbedaan antara pejabat yang mengelola negara dengan nurani dan pejabat yang mengelola negara dengan gengsi.
Sikap Purbaya juga membawa implikasi politik yang signifikan. Dalam konteks pemerintahan yang sering diwarnai figur-figur kuat dan dominasi pengaruh personal, menolak gagasan tokoh besar seperti Luhut Binsar Pandjaitan bukan keputusan ringan. Namun, di situlah nilai kepemimpinan sejati diuji keberanian untuk berkata tidak terhadap hal yang salah, meski dihadapkan pada risiko politik.
Tindakan ini menjadi contoh nyata bagi birokrat dan pejabat publik bahwa loyalitas sejati bukan kepada individu, tetapi kepada prinsip dan amanah jabatan. Purbaya, dengan tenang namun tegas, menunjukkan bahwa integritas fiskal tidak boleh dinegosiasikan, bahkan oleh kekuatan politik sekuat apa pun.
Kita membutuhkan lebih banyak pejabat seperti Purbaya yang tidak tergoda untuk memoles citra melalui proyek megah, tetapi memilih menjaga marwah negara dengan ketegasan.
Sebab keberhasilan pemerintahan bukan diukur dari banyaknya proyek, melainkan dari bersihnya hati dan rasionalitas dalam mengelola uang rakyat.
Tindakan ini seharusnya menjadi momentum bagi kementerian dan lembaga lain untuk mengembalikan semangat akuntabilitas dan efisiensi.
Jika setiap pejabat memiliki keberanian moral yang sama, maka sistem fiskal Indonesia tidak hanya kuat di angka, tetapi juga bermartabat di hati rakyat.
Sikap Purbaya bukan sekadar pernyataan teknis keuangan, melainkan manifesto etika kepemimpinan.
Ia menegaskan bahwa negara ini masih punya pejabat yang tidak menjual prinsip demi proyek. Bahwa di tengah arus politik yang sering keruh, masih ada keberanian untuk menjaga beningnya nurani.
Indonesia tidak butuh pejabat yang pandai beretorika tentang efisiensi, tetapi pejabat yang punya nyali untuk menolak penyalahgunaan fiskal.
Purbaya telah menulis bab kecil tentang integritas dalam buku besar pemerintahan bab yang seharusnya dibaca dan dicontoh oleh siapa pun yang mengaku bekerja untuk rakyat. (*)
Apa Reaksimu?