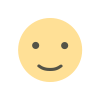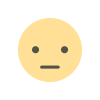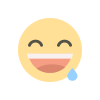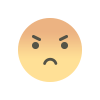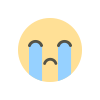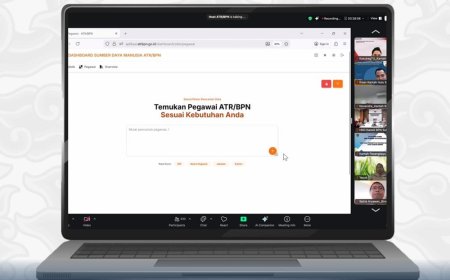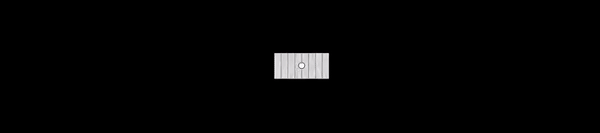PBB, Antara Retorika Politik dan Ilusi Perdamaian: Analisis Pidato Prabowo, Trump, dan Sukarno
Oleh: Mohsen Hasan A., Pemerhati Sosial, Politik, Budaya, Isu Global - Dewan Pakar DPP Partai NasDem

SIDANG Umum PBB selalu menjadi panggung bagi para pemimpin dunia untuk memproyeksikan suara bangsanya. Namun, dari masa ke masa, sorotan pidato para presiden dunia justru menyingkap satu kenyataan pahit: PBB seringkali hanya menjadi ruang retorika politik, bukan alat nyata untuk menghadirkan keadilan global.
Tiga pidato—Prabowo Subianto, Donald Trump, dan Sukarno—dari era berbeda, memperlihatkan sisi paradoks ini dengan cara yang unik.
Soekarno 1960: “To Build The World Anew”
Pada tahun 1960, Soekarno tampil selama hampir dua jam dengan pidato monumental “To Build the World Anew.”
Ia lantang menyuarakan keresahan Asia-Afrika yang masih diguncang kolonialisme dan imperialisme.
Soekarno menegaskan bahwa perdamaian sejati belum pernah dirasakan bangsa Asia-Afrika karena dominasi Barat dan diamnya PBB terhadap agresi kekuatan besar.
Tepuk tangan bergemuruh dan standing ovation kala itu bukan sekadar penghormatan, melainkan simbol penerimaan Soekarno sebagai juru bicara dunia ketiga.
Pesan Soekarno jelas: selama PBB dikendalikan hak veto negara kuat, lembaga ini hanya jadi “penonton” ketidakadilan.
Trump 2017–2019: “America First” Di PBB
Donald Trump menggunakan panggung PBB untuk mempromosikan doktrin America First.
Pidatonya panjang, kadang ngalor-ngidul, penuh serangan terhadap negara lain seperti Iran, Korea Utara, dan Tiongkok.
Alih-alih menghadirkan narasi perdamaian, Trump menjadikan forum global itu sebagai panggung politik domestik AS.
Secara implisit, ia menegaskan bahwa PBB hanyalah alat ketika sejalan dengan kepentingan Washington, dan tak berguna jika menghambat.
Pesan tersiratnya: perdamaian hanyalah hak istimewa Barat, sementara konflik di luar orbitnya tidak lebih dari komoditas geopolitik.
Prabowo 2025: “Seruan Indonesia Untuk Harapan”
Dalam pidatonya yang ringkas—sekitar 15 menit—Prabowo Subianto menekankan solidaritas global, keadilan internasional, dan solusi dua negara bagi Palestina dan Israel.
Pidato ini terkesan sederhana, tapi relevan dengan isu paling panas: kegagalan PBB mendorong realisasi resolusi kemerdekaan Palestina.
Prabowo menggarisbawahi bahwa tanpa keberanian politik dunia, PBB hanya akan melahirkan resolusi “kosmetik” yang tak menyentuh akar persoalan.
Dengan gaya berbeda dari Soekarno yang revolusioner dan Trump yang populis, Prabowo mencoba memposisikan Indonesia sebagai suara moral moderat: berpihak pada kemerdekaan Palestina, sekaligus mengajak dunia menutup jurang ketidakadilan global.
Benang Merah: PBB dan Ilusi Perdamaian
Dari ketiga tokoh ini, kita menemukan pola yang sama: PBB gagal menjadi institusi yang netral dan efektif.
Soekarno menyoroti diamnya PBB saat Asia-Afrika ditindas.
Trump memperlihatkan bagaimana Barat hanya menggunakan PBB sebagai instrumen kepentingan.
Prabowo menegaskan betapa resolusi soal Palestina tinggal retorika, tanpa implementasi nyata.
Kenyataan pahitnya: perdamaian global selama ini lebih sering dinikmati Barat, sementara bangsa-bangsa lain hanya menerima sisa konflik, blokade, dan penindasan.
Pidato di PBB seakan menjadi cermin keterbatasan lembaga internasional itu sendiri.
Bagi Soekarno, PBB adalah simbol kemunafikan dunia Barat yang menutup mata terhadap kolonialisme.
Bagi Trump, PBB hanyalah alat tawar untuk menegaskan supremasi Amerika.
Bagi Prabowo, PBB tetap diperlukan, tapi harus didorong agar berani menjalankan resolusi—terutama terkait kemerdekaan Palestina.
Dengan demikian, tiga pidato ini menegaskan satu hal: selama PBB masih terbelenggu kepentingan veto dan dominasi Barat, kedamaian global tidak lebih dari retorika politik. (*)
Apa Reaksimu?